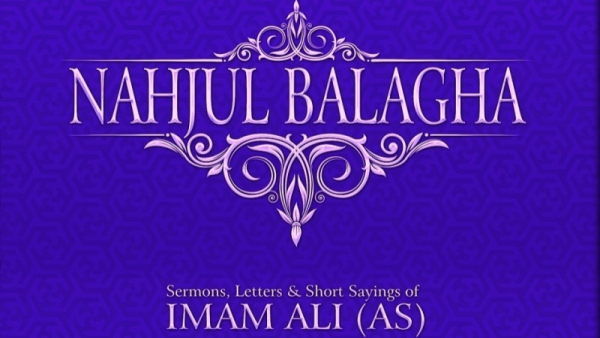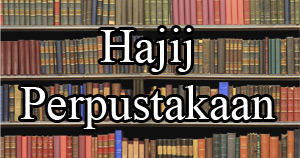Jurnalis Palestina, Shatha Hanaysha, sedang bersama Shireen Abu Aqla (kadang ditulis Abu Akleh) ketika mereka diserang oleh sniper Israel, di Jenin, Tepi Barat. Dalam tulisan ini, dia menggambarkan menit-menitu saat terbunuhnya Shireen, dan kenangannya atas Shireen, jurnalis yang sangat dikaguminya dan membuatnya sejak kecil bercita-cita untuk menjadi jurnalis juga. [Kisah ini disampaikan Shatha Hanaysha kepada penulis Shatha Hammad and Huthifa Fayyad.]
**
Shireen Abu Aqla (kiri), Shatha Hanaysha (kanan)
Sebelum saya pergi tidur tadi malam, saya terpaku pada ponsel saya memantau berita tentang tentara Israel yang meningkatkan pasukan di dekat pos pemeriksaan Jalame, di luar Jenin, sebuah kota Palestina di Tepi Barat yang diduduki.
Saya tahu ini berarti kemungkinan akan terjadi serangan di kamp pengungsi, seperti yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Saya meninggalkan ponsel saya dalam mode umum sehingga peringatan apa pun akan masuk, dan memutuskan untuk tidur beberapa jam agar siap di pagi hari.
Dan tepat sebelum pukul enam pagi, saya menerima telepon.
“Ada penggerebekan di kamp, apakah kamu ingin meliputnya?” rekan saya Mujahed al-Saadi bertanya.
”Tentu saja,” jawab saya. Saya bersiap-siap dan menuju Jenin dari rumah saya di kota Qabatya, 10 menit perjalanan dengan mobil.
Ketika saya tiba di dekat “Bundaran Kembali”, sebuah monumen besar di kota yang mengarah ke kamp, saya mengenakan helm pers dan pelindung tubuh, seperti yang dilakukan para jurnalis lain yang bersama saya.
Di luar kamp, Jenin terlihat tenang. Pagi itu terlihat normal, orang-orang berjalan dan mengemudi untuk bekerja dengan damai.
“Tidak ada yang perlu ditakuti,” seorang pejalan kaki yang datang dari kamp memberi tahu kami saat kami mengenakan rompi. “Hampir tidak ada yang terjadi di sana, tenang.”
Pasukan Israel telah menyerbu kamp dan mengepung rumah Abdallah al-Hosari, yang telah mereka bunuh pada 1 Maret, untuk menangkap saudaranya.
Sebelum kami berjalan kaki menuju kamp untuk meliput serangan dan baku tembak berikutnya antara pasukan Israel dan pejuang Palestina, kami berhenti untuk menunggu wartawan Al Jazeera.
Kejadian Chaos
Beberapa saat kemudian, Shireen Abu Aqla tiba dengan krunya. Inilah jurnalis gaya liputannya saya tiru sejak kecil, dari nada suara hingga gerakan tangan, dan saya bermimpi melakukan apa yang selalu dia lakukan dengan sangat baik. Itulah dia, Shireen, akan menjalankan peliputan yang sama dengan saya.
Shireen sedang bersiap meliput, beberapa menit sebelum ia ditembak Israel
“Selamat pagi,” sapa Shireen, saat dia, saya sendiri, dua reporter lagi, dan dua juru kamera bersiap-siap.
Saya merasakan aura aneh di sekelilingnya saat itu. Saya tidak dapat menemukan kata yang tepat untuk menggambarkan apa yang saya rasakan. Dia seolah ‘melayang’. Dia bahagia.
Kami membuat diri kami terlihat oleh tentara yang ditempatkan ratusan meter dari kami. Kami tetap diam selama sekitar 10 menit untuk memastikan para tentara tahu bahwa kami ada di sana sebagai jurnalis.
Ketika tidak ada tembakan peringatan ke arah kami, kami bergerak menanjak menuju kamp.
Entah dari mana, kami mendengar suara tembakan pertama.
Saya berbalik dan melihat rekan saya Ali al-Sammoudi tergeletak di tanah. Sebuah peluru mengenai punggungnya tetapi lukanya tidak serius dan dia berhasil menjauh dari lokasi.
Selanjutnya kekacauan terjadi. Rekan saya Mujahed melompati pagar kecil di dekatnya untuk menjauh dari peluru.
“Kemarilah!” serunya padaku dan Shireen, tapi kami berada di seberang jalan dan tidak bisa mengambil risiko untuk menyeberang.
“Al-Sammoudi terkena!” teriak Shireen, berdiri tepat di belakangku, saat kami berdua berdiri dengan punggung menghadap dinding untuk berlindung.
Saat itulah, peluru lain menembus kepala Shireen, dan dia jatuh ke tanah tepat di sebelah saya.
Saya memanggil namanya tapi dia tidak bergerak. Ketika saya mencoba mengulurkan tangan untuk menjangkaunya, peluru lain ditembakkan, dan saya harus tetap bersembunyi di balik pohon.
Pohon itu menyelamatkan hidup saya, karena itu adalah satu-satunya yang menghalangi pandangan tentara terhadap saya.
“Mundur, mundur!” teriak rekan-rekan saya, saat peluru beterbangan setiap kali saya mencoba memeriksa denyut nadi Shireen.
Entah dari mana, seorang penduduk kamp berhasil mencapai kami dengan mobil dari gang yang jauh dari jangkauan tentara Israel. Dia dengan cepat menarikku dan tubuh Shireen dan mengantar kami ke rumah sakit.
Mereka Bertujuan untuk Membunuh
Saya masih shock.
Apa yang terjadi adalah upaya yang disengaja untuk membunuh kami. Siapa pun yang menembak kami, bertujuan untuk membunuh. Dan adalah penembak jitu Israel yang menembak ke arah kami. Kami tidak terjebak dalam baku tembak dengan pejuang Palestina seperti yang diklaim tentara Israel.
Tidak ada pertempuran saat itu. Lokasi kejadian berada di area yang relatif terbuka, jauh dari kamp dimana pejuang Palestina tidak dapat bertindak karena mereka akan dirugikan jika bergerak di sana.
Jenis tembakan adalah indikasi lain. Pejuang Palestina biasanya menggunakan senapan semi-otomatis yang menyemprotkan peluru secara terus menerus. Peluru ini berbeda. Mereka sporadis dan tepat. Mereka hanya menembak ketika salah satu dari kami bergerak. Satu peluru pada satu waktu.
Saat itu saya tidak tahu, bagaimana akhir nasib saya hari itu, tetapi selama beberapa saat, saya telah bersiap untuk mati. Jenin telah berada di bawah serangan intensif Israel dalam beberapa bulan terakhir. Setiap kali saya meliput serangan itu, saya merasa akan dibunuh.
Israel tidak membedakan antara tua dan muda, pria dan wanita, jurnalis sipil dan kombatan. Setiap orang adalah sasaran.
Kenangan Atas Shireen
Di rumah sakit kami semua kaget. Jurnalis, petugas medis, dan warga Jenin.
Seperti banyak reporter lainnya, saya sangat terpukul. Setiap kali saya meletakkan telepon saya untuk memfilmkan, lengan saya lemah. Saya ingin melakukan pekerjaan saya dan mendokumentasikan adegan itu, tetapi saya juga ingin menghormati Shireen di saat terakhir.
Saya ingat diri saya sebagai seorang anak menonton dia menyampaikan liputannya di TV selama Intifadah Kedua.
Saya berusia sekitar tujuh tahun saat itu, dan sejak itu saya tahu persis apa yang saya inginkan ketika saya dewasa: saya ingin menjadi seperti Shireen.
Saya ingat ketika orang tua dan kakek-nenek saya akan duduk-duduk di ruang tamu dan berkata: “Shatha, ayo, beri kami laporan gaya Shireen.”
Ketika saya mengatakan ini padanya, dan bahwa dia adalah idola saya, dalam pertemuan pertama kami beberapa tahun yang lalu, dia tersenyum dan bercanda dengan saya.
Dia rendah hati pada saya, baik hati, dan manis.
Dia datang ke Jenin beberapa minggu yang lalu setelah bertahun-tahun tidak melapor dari kota ini. Saya pergi untuk menyambutnya, tidak menyangka dia akan mengenali saya, karena pastilah dia telah bertemu sangat banyak jurnalis muda lainnya.
“Bagaimana kabarmu Shatha?” katanya saat melihat saya, mengingat nama saya, membuat saya terkejut sekaligus senang.
Kisah-kisah seperti inilah yang mungkin akan diingat sebagian besar dari kita, saat tubuhnya dibawa berkeliling Jenin untuk dikenang.
Kami akhirnya tiba di biara kecil di kota dan lonceng gereja mulai berbunyi untuk Shireen, yang berasal dari keluarga Kristen dari Betlehem.
Di sekitar jenazah Shireen, kami semua berdiri sebagai Muslim dan Kristen, mendengarkan doa Imam dalam diam.
Ketika saya melihat sekeliling, saya melihat beberapa kamera sedang merekam. Di belakang masing-masing adalah seorang jurnalis Palestina yang terisak-isak, mengetahui bahwa Shireen tidak akan pernah berada di ujung lensa itu lagi.
Sebagai warga Palestina dan jurnalis, kehilangan kami tak terlukiskan. Tapi sekarang, lebih dari sebelumnya, pekerjaan kami menjadi semakin penting. Untuk mendokumentasikan kejahatan rezim pendudukan ini, untuk nilai jurnalistik kita, untuk kebenaran, dan untuk Shireen.