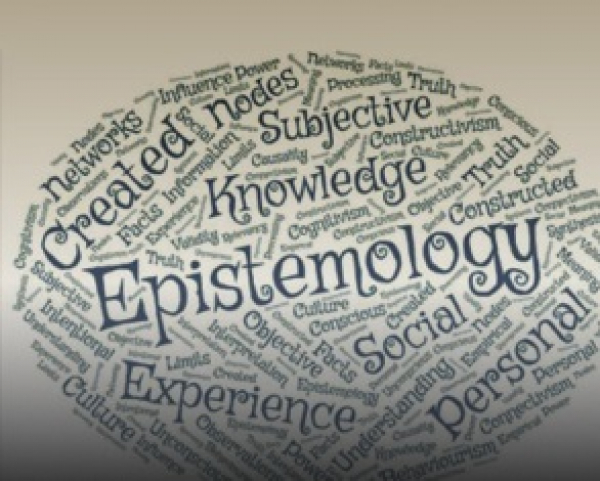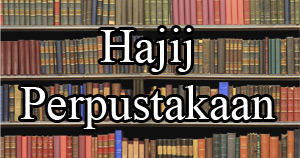کمالوندی
Siapakah ayah Ibrahim yang sebenarnya?
Siapakah ayah Ibrahim yang sebenarnya? Apakah ayahnya adalah penyembah berhala? Apakah setiap nabi itu harus dari keturunan yang suci?
Jawaban Global
Pertanyaan ini dapat dibagi menjadi dua bagian:
1. Tentang ayah nabi Ibrahim As.
2. Tentang ayah seluruh nabi.
Sehubungan dengan persoalan pertama terdapat dua pandangan:
1. Sebagian ulama Ahlusunnah berkeyakinan bahwa ayah nabi Ibrahim As adalah penyembah berhala dan namanya adalah Azar.
2. Sebagian ulama Ahlusunnah lainnya dan seluruh kaum Syiah berkeyakinan bahwa ayah, ibu dan seluruh kakek-nenek para nabi yang di antaranya adalah Nabi Ibrahim As sama sekali tidak ada yang musyrik dan tidak pernah menyembah berhala. Bahkan mereka semua adalah muwahhid (meng-esakan Tuhan) dan menyembah Allah Swt. Adapun nama ayah Nabi Ibrahim As adalah Tarikh.
Terdapat empat ayat dalam Al-Qur'an yang menyebutkan kata "ab" terkait dengan Azar namun yang maksudnya adalah bukan ayah, melainkan paman Nabi Ibrahim As. Berdasarkan berbagai riwayat yang dinukil dari Rasulullah Saw bahwa seluruh kakek-nenek beliau Saw sampai kepada nabi Adam As adalah orang-orang yang muwahhid (bertauhid). Dalam hal ini Rasulullah Saw bersabda: "Aku senantiasa berpindah-pindah dari sulbi-sulbi yang suci kepada rahim-rahim yang suci". Sesuai dengan nukilan hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa ayah Nabi Ibrahim As tidak mungkin seorang yang musyrik. Karena itu, kata "ab" pada ayat tersebut bukan bermakna ayah, tetapi bermakna paman atau ayah isteri atau lainnya. Terdapat pada ayat lainnya bahwa kata "ab" dimaksudkan sebagai makna kakek, paman dan ayah hakiki. Karena itu, jika dikatakan bahwa Azar yang dalam al-Qur'an diungkapkan dengan redaksi "ab", maka maksudnya adalah paman Nabi Ibrahim As. Sesuai dengan kamus istilah al-Qur'an bahwa makna tersebut mempunyai landasan yang kuat. Dalam riwayat-riwayat Syiah dijelaskan bahwa ayah hakiki Nabi Ibrahim As itu bernama Tarikh, kitab Taurat pun mengokohkan pandangan ini. Adapun apakah setiap nabi itu harus dari keturunan yang suci? Terdapat riwayat yang dinukil dari Rasulullah Saw bahwa "Tidak seorang pun dari seluruh ayah dan ibuku (datuk-datuk) itu pernah menyentuh perbuatan keji (zina). Riwayat ini juga meliputi seluruh kakek-nenek beliau Saw. Mengingat bahwa tolok ukur kesucian ayah-ibu seluruh nabi itu sama, maka berdasarkan kaidah "tanqihu al-manâth" (memutuskan suatu hukum berdasarkan kesamaan tolok ukur), hukum ini dapat meliputi seluruh para nabi.
Jawaban Detil
Pertanyaan ini dapat dibagi menjadi dua bagian:
1. Tentang ayah nabi Ibrahim As.
2. Tentang ayah seluruh nabi.
Sehubungan dengan persoalan pertama terdapat dua pandangan:
1. Sebagian ulama Ahlusunnah berkeyakinan bahwa ayah nabi Ibrahim As adalah penyembah berhala dan namanya adalah Azar.
2. Sebagian ulama Ahlusunnah lainnya dan seluruh kaum Syiah berkeyakinan bahwa ayah, ibu dan seluruh kakek-nenek para nabi dan di antaranya adalah Nabi Ibrahim As, sama sekali tidak ada yang musyrik dan tidak pernah menyembah berhala. Bahkan mereka semua adalah orang-orang yang muwahhid (meng-esakan Tuhan) dan menyembah Allah Swt. Adapun nama ayah Nabi Ibrahim As adalah Tarikh.
Boleh jadi sumber perbedaan ini adalah ayat-ayat yang terdapat dalam al-Qur'an. Karena dalam al-Qur'an terdapat ayat yang menggunakan kata "ab"
untuk seseorang yang bernama Azar yang biasanya (tanpa indikasi) digunakan sebagai makna ayah. Dengan itu, maka ayat-ayat tersebut harus dikaji terlebih dahulu, kemudian setelah meneliti dan memecahkannya barulah kami akan menjawab pertanyaan Anda.
Terdapat empat ayat di dalam Al-Qur'an yang menggunakan kata "ab" sekaitan dengan Azar :
1. "Dan permintaan ampun dari Ibrahim (kepada Allah) untuk ayahnya (pamannya Azar), tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu (agar ia tertarik kepada keimanan). Akan tetapi tatkala telah jelas bagi Ibrahim, bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun." (Qs. Al-Taubah [9]: 114).
2. "Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya (pamannya) Azar: "Pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai tuhan-tuhan? Sesungguhnya aku melihat bahwa kamu dan kaummu berada dalam kesesatan yang nyata." (Qs. Al-An'am [6]: 74)
3. "Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya (pamannya: Azar) dan kaumnya: "Sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu sembah." (Qs. Al-Zukhruf [43]: 26)
4. "Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya (pamannya): "Sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan (kepada Allah) bagi kamu dan aku tiada dapat menolak sesuatupun dari (siksaan) Allah." Qs. Al-Mumtahanah [60]:
Pada ayat pertama, Allah Swt telah menjelaskan bahwa ayah (paman) Ibrahim sebagai musuhnya dimana beliau berlepas diri darinya. Dan pada ayat yang kedua Ibrahim mengatakan bahwa Azar berada dalam kesesatan yang nyata. Dan pada ayat yang ketiga Ibrahim As berkata bahwa beliau berlepas tangan dan tidak bertanggung jawab atas apa yang ia sembah. Adapun pada ayat yang keempat Ibrahim As berkata kepada Azar (berjanji kepadanya) bahwa beliau akan memintakan ampunan kepada Allah untuknya. Tetapi dengan memperhatikan ayat pertama yang menjelaskan bahwa Allah Swt berfirman: "Maka tatkala telah jelas bagi Ibrahim, bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya."
Maksud dari kata "Ab"
Berdasarkan tanda-tanda dan beberapa bukti yang akan kami jelaskan di bawah ini, menjadi jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan kata "Ab" pada ayat-ayat tersebut adalah paman Ibrahim As .
Berdasarkan berbagai riwayat yang datang dari Rasulullah Saw yang dinukil baik oleh mazhab Sunni maupun Syiah bahwa seluruh kakek-nenek beliau Saw sampai kepada Nabi Adam As adalah orang-orang yang muwahhid (bertauhid).[1] Dalam hal ini Rasulullah Saw bersabda: "Aku senantiasa berpindah-pindah dari sulbi-sulbi orang-orang yang suci kepada rahim-rahim wanita-wanita yang suci".[2] Dalam hadis yang lain Nabi Saw bersabda: "Allah senantiasa memindahkanku dari sulbi-sulbi orang-orang yang suci kepada rahim-rahim para wanita suci hingga akhirnya Dia mengeluarkanku di alam duniamu ini, dan sama sekali aku tidak tersentuh oleh kotoran-kotoran jahiliyah".[3]
Sudah jelas bahwa ketika Rasulullah Saw adalah keturunan Nabi Ismail dan Ibrahim As, maka secara otomatis bahwa ayah Ibrahim As merupakan kakek Rasulullah Saw yang sesuai dengan hadis di atas tidak mungkin termasuk orang-orang yang musyrik. Dengan demikian bahwa kata "ab" di dalam ayat tersebut tidak mungkin diartikan dengan ayah. Tetapi bermakna lain sebagaimana makna yang biasa digunakan oleh orang-orang Arab, yaitu bemakna paman atau ayah isteri. Dalam al-Qur'an, Allah Swt menyebutkan Nabi Ismail yang merupakan paman Nabi Ya'qub As, sebagai ayahnya. Allah Swt berfirman: "Apakah kamu hadir ketika Ya'qub kedatangan (tanda-tanda) kematiannya, ketika ia berkata kepada anak-anaknya: "Apa yang akan kamu sembah nanti sepeninggalanku?". Mereka menjawab: "Kami akan menyembah Tuhanmu dan tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishaq, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan kami hanya tunduk penuh kepada-Nya." (QS. Al-Baqarah [2]: 133)
Dalam ayat tersebut kata "ab" diartikan sebagai kakek, paman dan ayah yang sesungguhnya. Karena itu, jika dikatakan bahwa Azar yang dalam al-Qur'an diungkapkan dengan kata "Ab", maka maksudnya adalah paman Ibrahim As. Dan sesuai dengan kamus istilah al-Qur'an hal itu mempunyai dalil yang kuat.
Sesungguhnya ayah Ibrahim yang hakiki adalah orang lain dan bukan Azar. Tetapi Al-Qur'an tidak menjelaskan namanya. Dalam riwayat-riwayat Syiah namanya adalah Tarikh. Kitab Taurat pun mengokohkan pandangan ini.[4] Ummu Salamah, isteri Rasulullah Saw berkata: "Aku pernah mendengar Rasulullah Saw bersabda: "Adnan adalah Ad putera Udud bin Ilyasa' bin Humaisa' bin Salaman bin Nabat bin Haml bin Qaidar bin Ismail bin Ibrahim As bin Tarikh bin Takhur bin Sarukh bin Ar'awa' bin Faligh bin 'Abir dan dia adalah Hud As bin Syalikh bin Arfakhsyad bin Sam bin Nuh As bin Lamak bin Matusylakh bin Akhnukh, dia adalah Idris bin Yarid bin Mahlail bin Qainan bin Anusy bin Syits bin Adam As; bapak manusia.[5] Karena itu, ayah Ibrahim adalah Tarikh, sedangkan Azar adalah pamannya.[6]
Tidak diragukan bahwa kaum musyrikin dan para penyembah berhala adalah merupakan musuh-musuh Allah Swt dan bagi setiap Muslim diwajibkan berlepas diri dari semua musuh Allah tersebut, bukan malah berlemah lembut dan menaruh simpati kepada mereka. Dengan itu kita saksikan, ketika telah jelas bahwa paman Ibrahim As; Azar adalah merupakan musuh Allah, beliau segera menyatakan berlepas diri dan tidak bertanggung jawab atas sikap dan perbuatannya itu. Allah Swt di dalam Al-Qur'an -dengan menukil ucapan Ibrahim- berfirman: "Maka ketika telah jelas baginya bahwa dia (Azar, pamannya) adalah musuh Allah, maka ia tidak bertanggung jawab terhadapnya." (Qs. Al-Taubah [9]: 114)
Apakah setiap nabi harus dari keturunan yang suci?
Al-Suyuthi dalam al-Durr al-Mantsur - terkait dengan ayat yang "wa laqad ja'akum Rasulun min anfusikum,"[7]- menyatakan: "Abu Na'im dalam kitabnya Dalâil meriwatkan sebuah hadis dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Tidak seorang pun dari semua ayah dan ibuku pernah menyentuh perbuatan keji (zina), dan Allah Swt senantiasa memindahkanku dari sulbi ayah-ayah yang suci kepada rahim-rahim para ibu yang suci pula. Dan di mana saja ayah-ayah tersebut mempunyai anak-anak, maka aku dipindahkan ke sulbi seorang anak yang lebih suci dan lebih baik dari anak-anak lainnya.[8]
Riwayat ini juga meliputi seluruh kakek-nenek Nabi Saw. Mengingat bahwa tolok ukur kesucian ayah-ibu seluruh nabi itu sama, maka berdasarkan kaidah "Tanqihu al-Manâth" (menetapkan suatu hukum berdasarkan kesamaan tolok ukur), hukum ini dapat meliputi seluruh para nabi.
Kesimpulannya adalah bahwa berdasarkan banyak ayat dan riwayat yang bermacam-macam, baik melalui jalur Sunni maupun Syiah, demikian juga berdasarkan akal dan ijma' dapat dipahami bahwa kedua orang tua (ayah ibu) nabi Ibrahim As adalah termasuk orang-orang yang muwahhid (meng-esakan Tuhan) dan orang-orang yang suci.
Dengan itu maka keyakinan kami, bukan hanya kaum Syiah bahkan banyak dari kaum Sunni meyakini bahwa ayah dan ibu semua nabi dan nabi Ibrahim As hingga Nabi Adam As, sama sekali tidak pernah ternodai oleh syirik. Mereka adalah orang-orang yang muwahhid dan orang-orang yang suci dari perbuatan zina dan melahirkan keturunan dengan cara pernikahan secara syar'i.[IQuest]
[1]. .Alusi, Sayyid Mahmud, Ruh al-Ma'âni fi Tafsiri al-Qur'ân, Ali Abdul Bari Athiyyah, jil. 7, hal. 388, Dar al-Kutub Al-'Ilmiyah, Cet. Beirut, 1415 H. Cet. 1; Andalusi, Abu Hayyan Muhammad bin Yusuf, bin Hayyan, al-Bahrul al-Muhith fi al-Tafsir, jil. 8, hal. 439 Al-Bahru Al-Muhith, Situs Tafsir, http://www.altafsir.com (Al-Maktabah Al-Syamilah); Razi, Abu Abdillah Fakhruddin Muhammad bin Umar, Mafâtih al-Ghaib, jil. 6, hal. 337, Daru Ihya Al-Turats Al-Arabi, Beirut, 1430 H, Cet. III; Ibnu Adil, Tafsir Al-Lubab, jil. 7, hal. 9, Situs Al-Tafsir, http://www.altafsir.com (Al-Maktabah Al-Syamilah).
[2] .Alusi, Sayyid Mahmud, Ruh al-Ma'âni fi Tafsiri al-Qur'ân, jil. 7, hal. 388; Andalusi: Abu Hayyan Muhammad bin yusuf, a-Bahr al-Muhith fi al-Tafsir, jil. 8, hal. 439; Razi, Abu Abdillah Fakhruddin, Muhammad bin Umar, Mafâtih al-Ghaib, jil. 6, hal. 337; Ibnu Adil, Tafsir Al-Lubâb, jil. 7, hal. 9 dan .....(Yang menarik adalah bahwa Alusi kurang begitu memperhatikan ucapan Fakhru Al-Razi yang mengatakan bahwa ucapan ini khusus Syiah).
[3] . Riwayat ini banyak dinukil oleh para mufassir baik Syiah maupun Sunni, seperti al-Thabarsi dalam kitabnya Tafsir Majma'u al-Bayân, Neisyaburi di dalam kitab tafsir Gharâibu al-Qur'ân, Fakhru Al-Razi di dalam kitab tafsir Al-Kabir dan Alusi di dalam kitab tafsir Ruh al-Ma'âni fi Tafsiri al-Qur'ân..
[4] .Baihaqi, Dalâil al-Nubuwwah, jil. 1, hal. 103, Situs Jami'u al-Ahadits, http://www.alsunnah.com (Al-Maktabu Al-Syamilah).
[5] .Thabarsi, Fadhl bin Hasan, I'lâmi al Warâ bi A'lami al-Hudâ, hal. 6.
[6].Kulaini, Raudhat al-Kâfi, Terj. Kamerei, jil. 2, hal. 327, Cet. Darul Al-Kutub Al-Islamiyah, Tehran, th. 1365 Sy.
[7]. "Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin." (Qs. Al-Taubah [9]: 128)
Mengapa Allah Swt menggunakan kata ganti orang (dhamir) ketiga laki-laki untuk diri-Nya dalam al-Qur’an?
Sebab mengapa Allah Swt al-Qur’an menggunakan kata ganti orang ketiga laki-laki untuk diri-Nya adalah lantaran al-Qur’an diturunkan dalam bahasa Arab dan penggunaan kata ganti laki-laki (dhamir, pronomina) bagi Allah Swt telah sesuai dengan kaidah dan sastra bahasa Arab. Karena Allah Swt bukan muannats (feminim) hakiki dan juga bukan mudzakkar (maskulin) hakiki dan juga tidak menggunakan penggunaan qiyâsi (mengikuti kaidah tertentu) dan simâi muannats majâzi (figuratif). Karena itu, berdasarkan kaidah bahasa Arab yang harus digunakan untuk Zat Allah Swt adalah kata ganti-kata ganti dalam bentuk maskulin figuratif (mudzakkar majâzi). Di samping itu, tanda-tanda literal maskulin dan feminin bukan sebagai penjelas kedudukan dan derajat yang mengandung nilai (value).
Bahasa al-Qur’an adalah bahasa Arab. Bahasa Arab berbeda dengan bahasa-bahasa lainnya menggunakan dua jenis kata ganti dan pronomina (dhamir) orang ketiga laki-laki (mudzakkar) dan kata ganti orang ketiga perempuan (muannats). Suatu hal yang natural bahwa setiap buku atau kitab yang ingin ditulis menggunakan bahasa ini, kendati ia merupakan kitab Ilahi, maka ia harus mengikuti kaidah-kaidah bahasa tersebut dan gramatikanya.
Bahasa Arab, karena tidak memiliki kata ganti orang ketiga waria (khuntsa), sebagian hal yang tidak memiliki jenis kelamin dinyatakan dengan kata ganti orang ketiga laki-laki (dhamir mudzakkar). Namun, yang semisal dengan masalah ini, juga terdapat dalam bahasa-bahasa yang lain, seperti bahasa Prancis. Dengan bersandar pada poin ini dapat diambil kesimpulan bahwa pernyataan kata ganti orang ketiga laki-laki, sama sekali tidak ada kaitannya dengan sifat kelaki-lakian.
Pada kenyataannya, dapat dikatakan bahwa al-Qur’an tidak didominasi oleh pandangan patriarkial yang berkembang pada budaya zamannya, melainkan sebuah tipologi bahasa yang mengkondisikan pembicaranya supaya memperhatikan dan mematuhi hal tersebut. Karena itu, al-Qur’an, dengan alasan diturunkan dan diwahyukan dalam bahasa Arab, bertutur kata dengan wacana ini dan menggunakan pronomina-pronomina dan redaksi maskulin (mudzakkar) yang selaras dan sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab.
Dengan kata lain, dari satu sisi, dalam bahasa Arab, nomina-nomina (asmâ) dan verba-verba (af’âl) (selain verba kata ganti orang pertama tunggal [mutakkalim wahdah] dan kata ganti orang pertama jamak [mutakallim ma’a al-ghair]) memiliki dua jenis: laki-laki atau maskulin (mudzakkar) dan perempuan atau feminin (muannats). Maskulin dan feminin ini terbagi lagi menjadi hakiki dan majâzi (figuratif). Seluruh entitas yang memiliki alat kelamin pria dan wanita adalah maskulin dan feminin hakiki (mudzakkar dan muannats hakiki). Selainnya adalah figuratif (majâzi).
Maskulin hakiki seperti “rajul” (pria) dan “jamal” (unta jantan). Feminin hakiki seperti “imraat” (wanita) dan “naqah” (unta betina). Maskulin figuratif (mudzakkar majazi) seperti “qalâm” (pena) dan “jidâr” (dinding). Feminin figuratif (muannats majazi) seperti “dâr” (rumah) dan “ghurfah” (kamar). Penggunaan muannats majazi dalam hal-hal seperti nama-nama kota, anggota badan yang berpasangan memiliki kaidah dan dalam hal-hal lainnya tidak mengikut kaidah tertentu (qiyâsi) dan bersifat simâi. Simâi artinya bahwa yang menjadi kriteria adalah semata-mata mendengar orang-orang yang berbahasa Arab dan harus diperhatikan orang-orang Arab menggunakannya dalam bidang apa. Apabila hal tersebut bukan termasuk muannats hakiki dan muannats majâzi dan juga bukan mudzakkar hakiki maka tentulah ia merupakan mudzakkar majâzi.[1]
Dari sisi lain, karena Allah Swt tidak melahirkan juga tidak dilahirkan. Demikian juga tiada yang menyerupainya[2] dan juga bukan termasuk hal-hal yang terkait dengan penggunaan qiyâsi (mengikuti kaidah tertentu) dan simai muannats majâzi. Karena itu, berdasarkan kaidah bahasa Arab yang harus digunakan untuk Zat Allah Swt adalah kata ganti-kata ganti, nama-nama dan sifat-sifat dalam bentuk mudzakkar majâzi (maskulin figuratif).
Poin ini juga harus mendapat perhatian bahwa tanda-tanda literal muannats dan mudzakkar tidak mengandung nilai tertentu dan tidak menunjukkan tanda dan dalil atas kemuliaan dan kedudukan seseorang. Karena itu, apabila tanda-tanda literal mudzakkar, menunjukkan kemuliaan dan kedudukan tertentu seseorang, dan memiliki nilai tertentu, maka untuk selain manusia dan sebagian makhluk rendah seperti setan dan iblis... tidak boleh menggunakan kata kerja-kata kerja atau nomina-nomina atau pronomina-pronomina dan seterusnya yang memuat tanda-tanda literal mudzakkar.
Demikian juga, apabila tanda-tanda literal muannats merupakan dalil dan tanda kekurangan dan minus nilai maka entitas-entitas yang sarat nilai seperti matahari (syams), bumi (ardh), kaum pria (al-Rijal), air (ma’) dan sebagainya dan sebaik-baik perbuatan dan kedudukan seperti sembahyang (shalat), zakat, surga (jannat) tidak akan dinyatakan dalam bentuk literal muannats.
[1]. Sharf Sâdeh, hal. 28 dan 145.
[2]. Lam yalid wa lam yulad (Qs. Al-Ikhlas [114]:3). Laisa kamitsli syai (Qs. Al-Syura [42]:11)
[3]. Silahkan lihat, Zan dar Âine Jalâl wa Jamâl, Jawadi Amuli, hal. 78.
Apa tafsir dari ayat “Segungguhnya hari kiamat itu akan datang Aku merahasiakan (waktunya)”
Banyak dari para ulama tafsir dengan mengambil sanad riwayat dari Imam Shadiq As,[2] mereka mengatakan: kata-kata “Aku merahasiakan (waktunya)” ialah jenis mubâlaghah (hiperbol), maksudnya ialah “Waktu terjadinya hari kiamat sangat tersembunyi dan rahasia sekali sedemikian sehingga hal itu pun disembunyikan pula dari diriku (dari nabi Musa As).”[3]
Oleh itu makna dari ayat ini ialah: “Wahai Musa! hari kiamat pasti akan datang, adapun Aku merahasiakan tentang kedatangannya, dan Aku tidak akan mengatakannya kepada seorangpun walau kepada para nabi sekalipun, sehingga Aku dapat melihat siapa yang beriman dan mempersiapkan diri dengan terjadinya kiamat, dan juga siapa yang tidak beriman dan tidak mempersiapkan dirinya, dan masing-masing akan mendapatkan balasannya.”[4]
Dengan kata lain, sebab tersembunyinya hari kiamat adalah Allah ingin memisahkan dan mengenal antara orang-orang yang ikhlas dan orang-orang selainnya, lalu akan memberikan balasan kepada orang yang telah berusaha menjadi hamba yang baik.[5]
Dari sisi lain di karenakan waktu tepatnya masih belum di ketahui dan kemungkinan bisa terjadi setiap saat, kesimpulannya adalah kita harus selalu mempersiapkan diri.[6] [iQuest]
Mengapa ayat-ayat al-Quran lebih didominasi dengan ayat-ayat maskulin?
Mengapa ayat-ayat al-Quran lebih didominasi dengan ayat-ayat maskulin? Mengapa kebanyakan penyampaian-penyampaian al-Quran lebih banyak bercorak maskulin seperti: Âmanû (orang-orang yang beriman), kâfarû (orang-orang yang kafir), Qâla (ia berkata), ya’lamun (mereka mengetahui), alladzî (yang) dan alladzîna (orang-orang yang)?
Jawaban Global
- Kita dapat menetapkan khitab-khitab (penyampaian-penyampaian) al-Quran itu maskulin ketika ruh yang mendominasi lafaz-lafaz dan khitab-khitab itu bersandar pada jenis kelamin dan fokus pada pria. Dari berbagai ayat al-Quran dapat dipahami bahwa wacana yang mendominasi al-Quran itu banyak yang terfokus pada manusia (bukan jenis kelamin) seperti pada (Qs. Fathir [35]:15), (al-Nahl [16]: 97), (Ali Imran [3]:5). Dengan dalil ini dapat kita katakan bahwa pandangan dan tujuan al-Quran terhadap jinsiyyah (jenis kelamin) hanyalah untuk memberikan hidayah, baik kepada kaum lelaki maupun kaum wanita (Qs.. al-Baqarah [2]: 128).
- Kelebihan khusus bahasa, sastra dan budaya Arab (sebagai bahasa teks al-Quran) adalah:
- a) Ketika dalam suatu tema jumlah mudzakkar (maskulin) lebih banyak, maka lafaz yang digunakan adalah dalam bentuk mudzakkar (maskulin) seperti pada ayat tathhir (Qs. al-Ahzab: 33).
- b) Untuk tujuan menjaga kehormatan dan pakaian wanita sehingga dalam penggunaan lafaz mu’annats (feminim) pun jumlahnya lebih sedikit seperti ayat yang berkaitan dengan masalah perkawinan (Qs. al-Nur [24]: 33).
- c) Berdasarkan kaidah sastra Arab, pada beberapa tempat, dengan memerhatikan qarinah-qarinah kalâmi (indikasi-indikasi ucapan) atau hâli (keadaan, sikap), dapat disimpulkan bahwa dengan mengetengahkan lafaz mudzakkar, maka wanita pun sudah termasuk di dalam kandungan ungkapan tersebut. Akan tetapi, tidak pernah terjadi sebaliknya. Dengan demikian, maka dengan menghadirkan lafaz wanita (mu’annats), maka kaum lelaki akan dianggap keluar dari objek bahasan. Misalnya bahasan yang terdapat pada ayat 204-206 surah al-Baqarah (2) dan pada ayat 31 surah al-Isra’ (17).
- Sebagian dari sastra Arab—sehubungan dengan mudzakkar (maskulin) yang disampaikan oleh al-Quran, misalnya ketika menjelaskan hukum-hukum fiqih, tugas-tugas dan hak-hak laki-laki—terkadang saham aturan-aturan untuk kaum laki-laki dalam bahasan tersebut lebih dominan dibandingkan dengan saham wanita. Hal itu nampak kita saksikan pada pembahasan tentang hukum-hukum jihad, kiat-kiat mencari pasangan hidup (Qs. an-Nisa [4]: 19) Mayoritas para pembesar dan penguasa di dalam ayat-ayat al-Quran adalah kaum laki-laki (seperti para nabi, para pemimpin kekafiran dan lain-lain).
- Banyak sekali ayat al-Quran yang penyampaiannya itu ditujukan kepada masyarakat umum dan di sini lafaz-lafaz mudzakkar tidak menekankan pada jenis tertentu. Misalnya juga lafaz mudzakkar yang digunakan sehubungan dengan lafaz “tuhan” atau malaikat. Pada lafaz tersebut tidak memberikan pahaman untuk mudzakkar ataupun mu’annats. Misalnya, pada Surah al-Isra (17): 36, al-Qashash (28): 71, al-A’raf(7): 29, Fushshilat (41): 30, an-Nisa (4): 56 dan at-Thalaq (65): 2.
- Mengingat bahwa kaum Adam itu lebih banyak memikul berbagai macam tanggung jawab, karena itu mereka banyak disebutkan di dalam al-Quran. Misalnya seperti khitab yang ditujukan kepada mereka dengan redaksi: “Jagalah dirimu dan keluargamu dari sentuhan api neraka” (Qs. at-Tahrim [66]: 6).
- Sebagian ayat ketika mengisahkan berbagai peristiwa yang berkaitan dengan sebagian kaum lelaki, demi menjaga kesesuaian lafaz-lafaznya dengan orang-orang yang merupakan sebab turunnya ayat tersebut, menggunakan lafaz-lafaz mudzakkar. Misalnya kisah yang terdapat pada ayat wilayah yang berkaitan dengan Imam Ali as dan pada semua lafaz yang dituangkan dalam bentuk mudzakkar (Qs. al-Maidah [5]: 55).
- Sebagian ayat al-Quran menggunakan kedua-duanya, lafaz-lafaz mudzakkar dan juga mu’annats (Qs. al-Ahzab [33]: 35); (Qs. al-Nisa [34]: 32). Karena mengulang-ulang lafaz-lafaz dan dhamir mu’annats beberapa kali di sebelah lafaz-lafaz mudzakkar, akan membuat susunan kalam itu tidak seimbang dan tidak serasi dan hal itu juga akan menjadikan ayat itu panjang serta akan merusak balaghah dan kefasihannya.
‘Ala kulli hal, dalam pemikiran wahyu Ilahi, yang menjadi tolok ukur dan kelebihan adalah “takwa” dan bukan masalah jinsiyyah (jenis kelamin; mudzakkar atau mu’annats).
Jawaban Detil
Pendahuluan
- Dapat kita ketahui bahwa ungkapan umum al-Quran atau setiap tulisan dan ucapan itu sifatnya “mudzakkar” ketika ruh dan kondisi umum yang menguasai hal itu adalah kehadiran dan penampilan jenis kelamin (jinsiyyat). Demikianlah dapat kita saksikan bahwa si pembicara lebih memerhatikan penampilan kemampuan dan kelebihan laki-laki atau perempuan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan meneliti isi kandungan dan tujuan-tujuan ayat-ayat al-Quran. Al-Quran, ketika menekankan jenis kelamin tertentu, pasti dibalik itu memiliki hikmah dan tujuan. Berikut ini akan kitabahas.
Dengan mengkaji dan memerhatikan ayat-ayat di bawah ini, akan kita temukan bahwa hukum umum yang mendominasi ayat-ayat al-Quran adalah lebih dari sekedar jenis kelamin. Ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut:
Hai manusia, sesungguhnya kalian fakir di hadapan Allah. Sedang Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.[1] Barangsiapa yang melakukan amal saleh, baik laki- laki maupun perempuan dan dia beriman, maka sesungguhnya Kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya Kami akan memberi balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.[2] Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satu pun yang tersembunyi di bumi dan tidak (pula )di langit.[3] Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik- baiknya.[4]
- Pada dasarnya tujuan para nabi, kitab-kitab yang diturunkan dari langit dan al-Quran al-Karim adalah untuk kemajuan dan kesempurnaan manusia. Karena itu, persoalan jenis kelamin tidak dijadikan sebagai pokok pembahasan. Tetapi yang menjadi perhatian manusia adalah malapetaka dan petunjuk.
Dengan ungkapan lain, yang menjadi lawan manusia adalah satu maujud berbahaya yang bernama setan. Setan dengan pakaian kecongkakannya yang ia tunjukkan ketika ia diuji untuk sujud kepada Adam dan membakar hangus ibadah yang ia lakukan selama enam ribu tahun, dengan kemarahan semacam ini apa yang akan ia lakukan kepada kita?! Setan tidak menghendaki jiwa ataupun tanah dari kita. Setan hanyalah ingin menghancurkan keimanan dan kehormatan kita.[5]
Dengan demikian, usaha al-Quran adalah menyadarkan dan memberikan petunjuk, baik kepada laki-laki ataupun perempuan.[6]
Sebab dan hikmah kelelakian (mudzakkar) ungkapan-ungkapan al-Quran:
- Keistimewaan bahasa, kebudayaan, peradaban dan tradisi bangsa Arab:
Banyak ditemukan ayat-ayat al-Quran yang menguatkan bahwa al-Quran itu bahasa Arab. Karena itu, seluruh karakter ucapannya harus ditafsirkan dengan kaidah-kaidah bahasa Arab dan kebudayan Arab. Pada selain itu (jika tidak sesuai dengan kaidah di atas) kita belum bisa memanfaatkan “pemahaman dan cita rasa ‘urf yang sesuai”![7]
Sebagian kelebihan dan keistimewaan bahasa Arab adalah sebagai berikut.
1-1. Apabila dalam satu susunan ayat, bilangan laki-laki lebih banyak dari perempuan, maka penyampaian lafaz-lafaz yang harus digunakan adalah dengan memerhatikan sisi mayoritasnya.
Contoh: Pada ayat tathhir yang menjelaskan tentang kesucian dan kebersihan keluarga Nabi Saw, karena di dalamnya mencakup seorang perempuan, yaitu Sayidah Fathimah al-Zahra As, dan empat orang lelaki, maka jumlah dan kata-kata ganti yang digunakan bersifat mudzakkar. Hal itu untuk menjaga bilangan yang lebih banyak mudzakkar-nya: "Wa Yuthahhirakum." [8]
2-1. Dalam budaya masa lalu dan telah mengakar, merupakan sebuah tradisi—karena ghirah dan demi menjaga kehormatan—mereka tidak mau menjelaskan pekerjaan para wanita mereka walaupun sekedar ucapan. Sehingga dapat kita saksikan bahwa sebagian masyarakat ketika memanggil atau mengucapkan sesuatu kepada istri-istri mereka di hadapan selain keluarga muhrimnya, mereka berbicara dengan menggunakan bentuk kiasan seperti: “Ibunya Hasan”, “Mereka”, “Keluarga” dan lain-lain. Hal semacam ini pun terdapat di dalam ungkapan-ungkapan al-Quran dengan maksud menjaga kehormatan para wanita mereka dan menghindari untuk menyebutkan nama mereka secara langsung. Sebagaimana budaya Arab, maka dzauq (lisan) al-Quran pun sangat memerhatikan metode semacam ini.
Misalnya: Walaupun sebenarnya perkawinan itu merupakan keinginan bersama antara pemuda dan pemudi, namun al-Quran—ketika menasihati orang-orang yang memperoleh kesulitan materi sehingga tidak dapat menikah—menujukan ucapannya kepada para pemuda. Allah Swt berfirman: "Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya."[9]
Padahal banyak ditemukan anak-anak perempuan yang tidak berumah tangga dikarenakan tidak adanya kemampuan (dari sisi finansial), namun al-Quran menggunakan lafaz mudzakkar. Hal itu dilakukan untuk menjaga kehormatan pribadi para pemudi.
3-1. Sifat fanatik yang mendominasi kalangan lelaki (khususnya pada masa itu) terhadap jenis kelaminnya sebegitu kuat dari sejak dulu dan bahkan hingga sekarang, sehingga jika di tengah-tengah perkumpulan antara laki-laki dan perempuan ucapan ditujukan kepada kaum perempuan, maka kaum lelaki menganggap bahwa mereka tidak termasuk dalam ucapan tersebut. Namun ketika ucapan ditujukan kepada golongan pria, maka ucapan itu mencakup golongan wanita pula, dan mereka sendiri mengakui bahwa hal itu mencakup diri mereka! (Hal ini dapat Anda kaji dalam ilmu pengetahuan yang membahas tentang tingkah laku perempuan). Misalnya, ketika ucapan ditujukan pada sebuah masyarakat yang tenggelam pada alam dunia dan materi yang ungkapan-ungkapan mereka menyebabkan orang menjadi heran, maka ucapan-ucapan tersebut ditujukan kepada laki-laki dan bukan kepada perempuan. Padahal keinginan duniawi itu ada pada kedua pribadi. Bahkan bisa jadi sifat materialisme dalam diri para wanita itu lebih dominan. Hal itu disebabkan jika digunakan dengan lafaz-lafaz yang sesuai pada wanita, maka kaum lelaki menganggap diri mereka terjauhkan dari celaan-celaan! Di antaranya firman Allah dalam al-Quran ayat 204-206 surah al-Baqarah. Allah berfirman: “Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu,…”
Atau ketika al-Quran ingin mencela perbuatan keji seperti membunuh anak kandungnya sendiri disebabkan takut hidup miskin, hal tersebut ditujukan kepada kaum pria.[10] Tentunya selain hikmah dan sebab budaya, terdapat sebab-sebab lain yang mendominasi peradaban kelaki-lakian al-Quran.
- Adanya hukum-hukum khusus berkaitan dengan kaum pria menuntut bahwa hanya dengan menggunakan lafaz-lafaz yang sifatnya mudzakkar sehingga sama sekali tidak mencakup wanita. Misalnya perintah-perintah khusus untuk kaum pria dalam tata cara membina keluarga[11] dan hukum-hukum yang berkaitan dengan talak yang dilakukan oleh laki-laki[12] dan hukum-hukum jihad yang khusus untuk kaum pria.[13]
- Topik dan kepribadian laki-laki banyak dibahas di dalam sebagian besar ayat al-Quran.[14] Tentunya di tempat yang dicantumkan nama peran perempuan tetap digunakan dengan memakai lafaz-lafaz perempuan (mu’annats) seperti peristiwa yang terjadi berkaitan dengan Sayidah Maryam as.[15] Sebagian besar dari ayat-ayat membahas khusus tentang para nabi as dan mereka juga dari kalangan laki-laki, seperti yang tercantum dalam beberapa surah seperti al-Najm (53): 3-4; al-Shaff: 6; al-Isra (17): 101; Saba (34): 10. Begitu juga dengan raja-raja yang kafir dari kalangan lelaki seperti Firaun, Namrud, Ashabul Fil dan lain-lain, atau ayat yang turun berkenaan dengan para tokoh dan pribadi-pribadi yang telah meninggal dan dengan tujuan menjaga keserasian ayat dengan sebab-sebab turunnya ayat, maka itu semua menggunakan lafaz-lafaz mudzakkar. Misalnya seperti ayat wilayah yang turun berkaitan dengan pemberian cincin yang dilakukan oleh Imam Ali bin Abi Thalib as. Allah Swt berfirman:"Sesungguhnya pemimpin kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman yang mendirikan salat dan menunaikan zakat seraya mereka tunduk (kepada Allah).”[16]
- Dalam sebagian besar ayat al-Quran walaupun kata ganti dan lafaz-lafaznya “mudzakkar” atau bahkan “muannats”, namun terkadang ucapan itu ditujukan kepada masyarakat dan lafaz itu tidak memiliki jenis kelamin. Hal ini persis seperti kata ganti mudzakkar yang dipakai pada Allah Swt tanpa harus dipahami bahwa Zat Yang Mahasuci adalah mudzakkar seperti contoh:
- Perintah al-Quran adalah bahwa tiada seorang pun yang berhak mengikuti para tokoh atau akidah-akidah tertentu dengan mata dan telinga tertutup dan tanpa ilmu pengetahuan tentangnya baik laki-laki atau pun perempuan! Namun ketika menyampaikannya dengan menggunakan lafaz mudzakkar tanpa ada jenis mudzakkar-nya, Allah berfirman: “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya…”[17]
- Begitu pula dalam beberapa ayat (manusia) telah diperintahkan untuk menimbang pada tanda-tanda (ciptaan) Allah Swt.[18]
- Dan dalam beberapa ayat (kita) diharuskan mengambil sebuah pondasi prinsip akidah yang benar dan memilih perantara untuk sampai pada Allah Swt.[19]
- Begitu pula dalam beberapa ayat yang menjelaskan tentang siksaan orang-orang ahli neraka tidak melihat pada jenis laki-laki ataupun perempuan.[20]
- Dan akhirnya dalam sebagian besar dari ayat-ayat al-Quran yang menyinggung tentang kematian, perhitungan (hisab) amal perbuatan, para malaikat, kenikmatan-kenikmatan, para penduduk surga, para penduduk neraka dan lain-lain sama sekali tidak dibatasi dengan jenis kelamin. Dengan ungkapan lain bahwa lafaz mudzakkar atau muannats sudah tidak lagi memiliki pemahaman laki ataupun perempuan, tetapi mencakup keduanya. (Sebagaimana yang kita ungkapkan dengan lafaz masyarakat), seperti pada ayat-ayat dalam beberapa surah al-Quran: al-Infithar (82): 19-12; al-An’am (6): 61; as-Sajdah (32): 11; al-Zumar (39): 42; al-Nahl (16): 50; Ali Imran (3): 133; Al-Thalaq (65): 2.
- Karena kaum lelaki memiliki pertanggungjawaban keluarga, sosial, ekonomi, koordinasi dan lain sebagainya, karena itu ucapan ditujukan kepada mereka; seperti: “Hai orang- orang (kaum lelaki) yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”[21]
Poin yang perlu diperhatikan adalah sebuah pertanyaan: mengapa pada ayat-ayat yang disebutkan di dalamnya para lelaki (kata ganti mudzakkar) dan tidak disebutkan batasan jenis kelamin dan sifatnya umum, disebutkan pula kaum perempuan (kata ganti muannats) di sisi kaum laki-laki (kata ganti mudzakkar)? Berkaitan dengan pertanyaan tersebut akan kami jawab pada poin keenam.
- Pengulangan nama perempuan di sisi lelaki—pada tempat yang lafaz mudzakkar mencakup keduanya—dapat menyebabkan perpanjangan kata atau ucapan dan dapat merusak kefasihan dan seni bahasa al-Quran.
Penjelasannya adalah bahwa:
Pada sebagian besar ayat al-Quran telah disinggung pula nama-nama perempuan di sisi laki-laki, misalnya seperti ayat: "Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki- laki dan perempuan yang mukmin,…” (Qs. Al-Ahzab [33]:35)
Atau ayat: “Bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan,…” (Qs. Al-Nisa [4]:32)
Nah, sekarang jika mesti terjadi dan dibahas pengulangan berkali-kali pada ayat-ayat lain dari sisi ini antara “perempuan-lelaki”, “lelaki-perempuan”, lelaki mukmin-perempuan mukminah demi tujuan keindahan atau pengetahuan kata dan hiasan-hiasan bahasa, maka hal ini sangat merusak kefasihannya dan dengan memperpanjang cara bicara dapat membuka ruang untuk mencela al-Quran.
Di akhir pembahasan ada satu poin yang kami anggap penting untuk diketahui, yaitu jika dibayangkan bahwa pengulangan-pengulangan yang banyak dari nama perempuan akan melazimkan sebuah penghormatan kepada kepribadian mereka dan ketiadaan pengulangan akan menyebabkan penghinaan, maka harus kita beritahu bahwa cara pengambilan sikap al-Quran tentang perempuan adalah merujuk pada ayat-ayat yang menjelaskan kedudukan perempuan dan juga menjelaskan kepentingannya dalam keluarga dan masyarakat dan peran teladan yang mereka miliki. Ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut:
Surah ar-Rum (30): 21; al-Baqarah (2): 228; Ali Imran (3): 36; al-Tahrim (66): 10-11; al-Hujuraat (39): 13; al-Baqarah (2): 187, dan jangan kita lupakan bahwa tolok ukur keutamaan adalah sifat “takwa” bukan pada kelaki-lakian (mudzakkar) atau keperempuanan (muannats).[]
[1]. Qs. Fathir (35): 15.
[2]. Qs. al-Nahl (16): 97.
[3]. Qs. Ali Imran (3): 5.
[4]. Qs. al-Tin (95): 4.
[5]. Abdullah Jawadi Amuli, Tausiyeh hâ va pursesh hâ, Penerbit Maarif, hal. 22.
[6]. Qs. Al-Baqarah (2): 128.
[7]. Qs. Yusuf (12): 2; Qs. Fushshilat (41): 3; Qs. al-Zumar (39): 28; Qs. as-Syu’ara (42): 193-195.
[8]. Qs. al-Ahzab (33): 33.
[9]. Qs. al-Nur (24): 33.
[10]. Qs. al-Isra (17): 31.
[11]. Qs. al-Nisa (4): 19.
[12]. Qs. al-Nisa (4): 20-21.
[13]. Qs. at-Taubah (9): 122.
[14]. Qs. an-Naml (27): 40.
[15]. Qs. at-Tahrim (66): 10.
[16]. Qs. al-Maidah (5): 55.
[17]. Qs. al-Isra (17): 36.
[18]. Qs. al-Qashash (28): 71; Qs. al-A’raf (7): 29.
[19]. Qs. al-Maidah (5): 35; Qs. Ali Imran (3): 85; Qs. Fushshilat (41): 30.
[20]. Qs. an-Nisa (4): 56.
[21]. Qs. al-Tahrim (66): 6.
Bagaimanakah epistemologi dalam pandangan Allamah Thabathabai?
Menurut Allamah media apakah yang paling ampuh dan kukuh dalam menetapkan kebenaran?
Apa perbedaan krusial antara epistemologi Mulla Sadra dan Allamah Thabathabai?
Salam sejahtera. Terima kasih sebelumnya atas kesediaan Anda menjawab pertanyaan saya. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimanakah epistemologi itu dalam pandangan Allamah Thabathabai? Menurut Allamah media apakah yang paling ampuh dan kukuh dalam menetapkan kebenaran? Apa perbedaan krusial antara epistemologi Mulla Sadra dan Allamah Thabathabai?
Jawaban Global
Secara ringkas dapat dikatakan bahwa secara umum para filosof Ilahi entah itu filosof Peripatetik (Massyâ'), filosof Iluminasi (Isyrâq), dan filosof Hikmah (Hikmah Muta'âliyah) bahkan para arif juga, berpendapat yang kurang lebih sama dalam masalah epistemologi; karena pertama, mereka meyakini bahwa dunia keberadaan adalah sesuatu yang ril dan faktual; mereka juga meyakini bahwa alam keberadaan memiliki nafs al-amr. Dengan kata lain, pandangan para filosof ini berseberangan dengan para sophis yang memandang alam keberadaan sebagai khayalan dan fantasi semata. Sementara filosof Ilahi mengakui realitas dan hakikat alam keberadaan.
Kedua, mereka meyakini bahwa realitas (pemahaman yang sesuai dengan kenyataan) itu sebagian ada; artinya alam keberadaan di samping ia ada, ia juga dapat ditemukan dengan perantara ilmu dan pengetahuan manusia dan manusia dapat mengenal alam keberadaan ini.
Ketiga, realitas (pemahaman yang sesuai dengan kenyataan) dalam pandangan mereka bersifat tetap dan permanen; artinya terdapat kesesuaian antara konsep dan kandungan pikiran dengan kenyataan dan nafs al-amr-nya tidak dapat bersifat temporal; melainkan bersifat permanen.[1]
Keempat, para filosof ini juga bersepakat terkait dengan media-media pengetahuan bahwa media-media dan jalan-jalan pengetahuan dalam pandangan mereka adalah: 1. Indra dan ilmu-ilmu eksperimental. 2. Akal dan argumen-argumen logis. 3. Penyingkapan dan penyaksian batin. 4. Wahyu.
Adapun yang dimaksud dengan media wahyu adalah hasil dan resultan wahyu. Hasil dan resultan wahyu merupakan salah satu media pengetahuan terhadap realitas yang terdapat pada setiap manusia; meski inti wahyu terkhusus untuk para nabi Ilahi.[2]
Poin utama yang harus mendapat perhatian adalah bahwa terkait dengan criteria standar dan nilai tiga jalan dan media pengetahuan pertama (indra, akal dan penyaksian) para filosof sedikit berbeda pendapat tentang hal ini. Dalam pandangan ahli makrifat dan irfan, penyingkapan dan penyaksian batin lebih utama; dalam pandangan mereka jalan yang paling meyakinkan untuk memahami realitas dan hakikat adalah melalui jalan penyingkapan (kasyf) dan penyaksian (syuhud) yang diperoleh melalui jalan sair dan suluk serta olah batin (riyâdhah).
Akan tetapi meski sandaran utama ahli makrifat adalah penyaksian batin dan memandang bahwa penyaksian batin lebih tinggi dari akal, namun mereka tidak memandang jalan akal bertentangan dengan jalan syuhud atau memandangnya sebagai sebuah perkara batil; melainkan dalam pandangan mereka akal yang penuh cahaya dan tidak terkontaminasi dengan pelbagai keraguan imaginasional dan ilusional, dapat berdaya guna untuk memahami realitas-realitas. Bahkan akal dapat membantu jalan penyingkapan dan penyaksian dalam memahami realitas.[3]
Dalam pandangan filsafat Peripatetik akal dan argumen-argumen logis lebih utama; dalam pandangan mereka, indra dan pengalaman juga tanpa bantuan akal tidak akan berguna bagi manusia dalam mencerap pengetahuan. Akan tetapi bersandar pada argumen-argumen rasional tidak bermakna pengingkaran terhadap penyaksian irfani; melainkan sebagian pengikut fisafat Peripatetik seperti Ibnu Sina berupaya mengelaborasi kasyf dan syuhud para arif dalam bahasa filosofis dan rasionalis.[4]
Filafat Iluminasi juga meski merupakan filsafat dzauqi, namun demikian mereka memandang penalaran dan filsafat penalaran sebagai dasar dan kemestiannya serta menilai pelatihan secara teratur akal teoritis dan fakultas penalaran merupakan tingkatan pertama kesempurnaan bagi para pencari makrifat. Dengan kata lain, filsafat Iluminasi adalah sebuah filsafat yang berupaya menciptakan hubungan antara dunia penalaran dan iluminasi atau pemikiran penalaran dan penyaksian batin.[5]
Dasar filsafat hikmah (Hikmah al-Muta'aliyah) juga membangun penjelasan pengetahuan-pengetahuan kasyf dan syuhud dengan bahasa filsafat dan akal; atas dasar itu, Mulla Sadra setelah mengelaborasi secara rasional sebagian masalah-masalah filsafat berkata, "Dengan kemurahan Allah Swt, kami menggabungkan antara dzauq dan wijdân, antara bahts dan burhân."[6]
Poin terakhir: Terkait dengan perbedaan pandangan Allamah Thabatahabai dan Mulla Sara dalam masalah epistemologi dapat dikatakan bahwa Allamah Thabathabai sembari mengakui kedudukan dan kemampuan syuhud batin dan jalan hati untuk memahami pelbagai realitas, namun secara keseluruhan apa yang menjadi perhatian utama Allamah Thabathabai dalam karya-karyanya adalah akal dan penalaran-penalaran rasional. Dengan kata lain, tidak ditemukan Allamah Thabathabai menjelaskan sesuatu dan beragumentasi dengan memanfaatkan kasyf dan syuhud batin; sebagai hasilnya nampaknya dalam pandangan Allamah Thabathabai, akal sebagai media kokoh dan bersifat umum bagi setiap manusia untuk menyingkap realitas.
Namun Mulla Sadra di samping ia merupakan seorang filosof rasionalis namun dalam karya-karyanya kita banyak menyaksikan masalah-masalah dzauqi dan syuhudi. Mulla Sadra dalam mukadiimah al-Asfar menyinggung sedikit tentang sekelumit biografinya dan perjalanan ilmunya, dan bagaimana ia dapat sampai pada level kasyf dan syuhud: "Kemudian saya mengalihkan perhatian secara instingtif terhadap Penyebab segala sesuatu (musabbib al-asbab) dan tunduk pada Sosok yang memudahkan pekerjaan-pekerjaan rumit. Kemudian setelah beberapa lama, saya dalam kondisi bersembunyi dan mengisolasi diri, dikarenakan oleh perjuangan dan perjalanan panjang, jiwaku memperoleh derajat cahaya yang tinggi dan hatiku menjadi cair disebabkan oleh pelbagai olah batin (riyâdhah). Sebagai hasilnya, jiwaku disinari cahaya-cahaya malakut, dihiasi ornamen alam jabarut dan dipendari cahaya-cahaya ahadiyat. "[7]
Sebagaimana Mulla Sadra dalam beberapa hal untuk mengelaborasi dan menetapkan masalah di samping menggunakan argumentasi juga memanfaatkan kasyf dan syuhud. Sebagai contoh kami akan menyinggung dua hal: 1. Kasyf dan burhan yang menjelaskan hal ini dan bersepakat bahwa seuruh entitas berada pada tataran untuk mencapai tingkatan tertinggi kebaikan dan cahaya yang lebih unggul (cahaya Allah Swt).[8]
2. Bagi kami kekuatan argumentasi dan cahaya kasyf serta syuhud tampak jelas. Ketiganya merupakan sumber tertinggi untuk meluaskan dan kekuatan eksistensial. Ketiganya merupakan sumber awal dan juga sumber akhir."[9] [iQuest]
[1]. Silahkan lihat, Murtadha Muthahhari, Ushûl Falsafah, jil. 1, hal. 103-108, Daftar Intisyarat Islami, Qum, Tanpa Tahun.
[2]. Silahkan lihat, Sayid Muhammad Husain Thabathabai, Syi'ah dar Islâm, hal. 74-100, Bustan Kitab, Qum, Cetakan Kelima, 1388 S.
[3]. Silahkan lihat, Yadullah Yazdanpanah, Mabâni wa Ushûl 'Irfân Nazhari, hal. 139-142, Muassasah Imam Khomeini, Qum, Cetakan Pertama, 1388 S.
[4]. Ibnu Sina bagian-bagian (Namath 8, 9, 10) kitab Isyarat mengkhususkan masalah ini; bahkan Namath 9 dinamai dengan "Maqâmat al-'Ârifin" yang membahas masalah ini.
[5]. Silahkan lihat, Syaikh Isyraq, Majmu'ah Mushannafât Syaikh Isyrâq, dengan mukadimah Sayid Husain Nashr, Mukaddimah, hal. 32, Muassasah Muthala'at wa Tahqiqat Farhanggi, Teheran, Cetakan Kedua, 1375 S.
[6]. Muhammad Shadr al-Muta'llihin (Mulla Sadra), al-Hikmat al-Muta'âliyah, jil. 8, hal. 143, Mansyurat Mustafawi, Qum, Tanpa Tahun.
[7]. Ibid, jil. 1, hal. 8.
[8]. Ibid, jil. 8, hal. 38.
[9]. Ibid, jil. 9, hal. 140.
Kapan haji mulai diwajibkan?
kapan haji mulai diwajibkan? Jawaban Global Berdasarkan riwayat, haji memiliki latar belakang yang sangat panjang dan sedemikian panjang sehingga sampai pada masa-masa sebelum penciptaan Nabi Adam As. Disebutkan bahwa setelah pelaksanaan haji Nabi Adam As usai, malaikat Jibril bersabda kepadanya, “Berbahagialah wahai Adam! Engkau telah dimaafkan. Aku bertawaf di sekeliling rumah (Ka’bah) ini tiga ribu tahun sebelumm
kapan haji mulai diwajibkan?
Jawaban Global
Berdasarkan riwayat, haji memiliki latar belakang yang sangat panjang dan sedemikian panjang sehingga sampai pada masa-masa sebelum penciptaan Nabi Adam As.
Disebutkan bahwa setelah pelaksanaan haji Nabi Adam As usai, malaikat Jibril bersabda kepadanya, “Berbahagialah wahai Adam! Engkau telah dimaafkan. Aku bertawaf di sekeliling rumah (Ka’bah) ini tiga ribu tahun sebelummu.”
Adapun tata cara dan urutan pelaksanaan haji kaum Muslimin dengan manasik-manasik seperti tawaf, sa’i, memotong hewan qurban, melempar jumrah, semuanya kembali pada masa-masa Nabi Ibrahim As. Karena secara pasti, peletak batu pertama haji secara resmi juga dilakukan oleh Nabi Ibrahim As dan Allah Swt memerintahkan kepadanya untuk mengumumkan haji dan menyeru orang-orang untuk datang berhaji ke rumah Ka’bah.
Jawaban Detil
Berdasarkan riwayat haji, memiliki latar belakang yang sangat panjang dan sedemikian panjang sehingga sampa pada masa-masa sebelum penciptaan Nabi Adam As seperti apa yang diungkap oleh Imam Shadiq As yang bersabda, “Setelah pelaksanaan haji Nabi Adam As usai, malaikat Jibril bersabda kepadanya, “Berbahagialah wahai Adam! Engkau telah dimaafkan. Aku bertawaf di sekeliling rumah (Ka’bah) ini tiga ribu tahun sebelummu.”[1]
Demikian juga Imam Shadiq As bersabda, “Setelah Nabi Adam kembali dari Mina (dan hajinya berakhir), para malaikat bertemu dengannya dan berkata kepadanya, “Wahai Adam! Hajimu berjalan baik! Kami menunaikan ibadah haji di rumah ini dua ribu tahun sebelummu.”[2]
Seseorang datang bertanya kepada Amirul Mukminin Ali As, “Siapakah penghuni langit yang pertama kali menunaikan haji?” Imam Ali As menjawab, “Jibril adalah malaikat penghuni langit yang pertama menunaikan ibadah haji.”[3]
Adapun tata cara dan urutan pelaksanaan haji kaum Muslimin dengan manasik-manasik seperti tawaf, sa’i, memotong hewan qurban, melempar jumrah, semuanya kembali pada masa-masa Nabi Ibrahim As. Karena secara pasti, peletak batu pertama haji secara resmi juga dilakukan oleh Nabi Ibrahim As dan Allah Swt memerintahkan kepadanya untuk mengumumkan haji dan menyeru orang-orang untuk datang berhaji ke rumah Ka’bah. Dalam hal ini, al-Quran menyatakan:
«وَ أَذِّنْ فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجالاً وَ عَلى کُلِّ ضامِرٍ یَأْتینَ مِنْ کُلِّ فَجٍّ عَمیق»
“Dan serulah seluruh manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh.” (Qs. Hajj [23]:27)
Akan tetapi sepanjang zaman – khususnya pada masa jahiliyah – haji Ibrahimi juga sebagaiman hukum-hukum lainnya mengalami penyimpangan. Berikut ini kami akan melampirkan sebagian amalan haji dan sebagian yang telah mengalami penyimpangan:
“Kemudian bertolaklah kamu (menuju Mina) dari tempat orang-orang banyak bertolak (‘Arafah) dan mohonlah ampun kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”[4]
Ayat ini menyoroti tentang salah satu tradisi orang-orang musyrik Mekkah pada masa jahiliyah dimana wukuf di Arafah hanyalah terkhusus bagi orang-orang yang datang dari luar kota Mekkah yang ingin menunaikan ibadah haji, namun Quraisy dan suku-suku di sekeliling kota Mekkah serta kerabat-kerabat Quraisy tidak termasuk dari perintah ini. Hal ini diungkap oleh Imam Shadiq tatkala menjelaskan ayat ini, “Orang-orang Quraisy berkata, “Kami lebih unggul atas Kabah ketimbang orang lain. Karena itu (untuk pelaksanaan haji) kalian mulai dari Muzdalifah (Masy’ar) dan tidak perlu pergi ke Arafah! Allah Swt memerintahkan kepada mereka untuk memulai dari Arafah sebagaiman orang lain.”[5]
“Sesungguhnya nasî’ (mengubah-ubah dan mengundur-undurkan bulan-bulan haram itu) adalah menambah kekafiran yang dengan tindakan ini orang-orang yang kafir disesatkan. Mereka menghalalkannya pada suatu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang Allah haramkan (dengan tujuan supaya mereka dapat menyempurnakan jumlah bilangan empat bulan haram itu). Maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Perbuatan mereka yang buruk itu dijadikan indah dalam pandangan mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.”[6]
Ayat mulia ini menyinggung tentang sebuah tradisi sesat masyarakat jahiliyah yang disebut sebagai nasi yang bermakna mengubah-ubah bulan-bulan haram itu dimana perbuatan ini setiap tahunnya dilakukan melalui sebuah perayaan khusus di Mina yang menunjukkan sikap pragmatis mereka; karena dengan mengubah dan mengganti tahun-tahun haram ini, mereka ingin penyelenggaran haji dilakukan sesuai dengan kepentingan dagang dan propaganda mereka. Karena itu, mereka berusaha supaya haji dilakukan pada hari-hari yang menyenangkan dan waktu-waktu mudah namun mengingat haji dilakukan pada hari-hari Dzulhijjah dan terkadang bulan Dzulhijjah panas matahari di Mekkah sangat terik dan menyengat sehingga membuat susah orang-orang yang menunaikan ibadah haji dan buntutnya dapat merubah kalkulasi perdagangan mereka. Oleh itu, dengan nasi mereka ingin musim haji dilakukan pada musim yang lebih sesuai dan cocok dengan kondisi mereka. Perbuatan ini berlanjut sampai tahun sepuluh Hijriah hingga Rasulullah Saw pada Hajjatul Widâ melarang perbuatan ini.[7] Dengan turunnya ayat ini, nasi dipandang sebagai perbuatan kufur sehingga pelaksanaan haji tidak menjadi alat permainan orang-orang pragmatis yang ingin mencari keuntungan.
“Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebagian dari syiar (dan tanda-tanda kebesaran) Allah. Maka barang siapa yang melakukan ibadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa (baca: larangan) baginya mengerjakan sai antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati (di samping kewajiban itu), sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri lagi Maha Mengetahui.”[8]
Salah satu amalan haji pada masa jahiliyyah, sai antara gunung-gunung Shafa dan Marwah namun di tas gunung ini, diletakkan dua berhala yang bernama Asaf dan Nailah sehingga kaum musyrik dapat memberi penghormatan pada dua berhala ini tatkala melakukan sai. Akibatnya, kaum Muslimin disebabkan oleh latar belakang tercela seperti ini enggan melakukan sai antara Shafa dan Marwah pada musim haji. Mereka mengira perbutan ini adalah perbuatan jahiliyah. Allah Swt dengan mewahyukan ayat ini, gambaran dan anggapan ini ditolak dan menyatakan bahwa sai antara Shafa dan Marwah merupakan salah satu syiar dalam agama, sebagaimana Muawiyah bin Ammar meriwayatkan dari Imam Shadiq As yang bersabda, “Kaum Muslimin beranggapan bahwa sai antara Shafa dan Marwah merupakan ciptaan orang-orang musyrik dan akibatnya Allah Swt menurunkan ayat mulia ini...”[9]
Salah satu tradisi jahiliyah lainnya pada pelaksanaan haji adalah melakukan thawaf dalam kondisi telanjang. Mereka meyakini bahwa penyediaan pakaian ihram berada di tangan Quraisy dan apabila ada seseorang tidak memiliki pakaian ihram maka ia harus melakukan thawaf dalam kondisi telanjang dan memandang batal mengenakana pakaian dan kain yang berasal dari luar haram. Imam Shadiq As bersabda, “Rasulullah Saw setelah menaklukkan kota Mekkah tidak menghalangi orang-orang musyrik melakukan ziarah baitullah dan salah satu kebiasaan ziarah orang-orang musyrik adalah bahwa apabila mereka mengenakan pakian memasuki Mekkah dan melakukan thawaf di sekeliling baitullah dengan pakaian yang sama, maka pakaian itu harus ditanggalkan dan sedekah pakaian itu menjadi wajib baginy. Karena itu supaya mereka tidak menanggalkan pakaian-pakaian mereka maka sebelum thawaf mereka menyewa dan meminjam pakaian dari orang lain dan mengembalikan pakaian itu kepada pemiliknya setelah menunaikan thawaf. Apabila seseorang tidak menemukan pakaian untuk dipinjam dan disewa dan ia hanya memiliki satu pakaian, supaya ia tidak kehilangan baju maka ia terpaksa harus melaksanakan thawaf dalam keadaan telanjang.”[10]
Dengan datang dan berkuasanya Islam, Rasulullah Saw bangkit melawan penyimpangan-penyimpangan kaum jahiliyah. Sembari memurnikan pelaksanaan haji dari penyimpangan-penyimpangan kaum jahiliyah, beliau menghidupkan kembali tradisi Nabi Ibrahim As; karena itu haji yang diterima dan dianjurkan Islam adalah haji yang sesuai dengan tradisi Nabi Ibrahim As dan syariat suci Islam juga, dengan bentuk yang sama, mewajibkan kaum Muslimin untuk melakukan hal yang sama, dan mengajarkan kepada kita manasik haji, syarat-syarat dan rukun-rukunnya. [iQuest]
[1]. Syaikh Shaduq, ‘Ilal al-Syarâ’i, jil. 2, hal. 407, Kitabpurusyi Dawari, Cetakan Pertama, Qum, 1385 S.
[2]. Syaikh Shaduq, Man Lâ Yahdhuruhu al-Faqih, jil. 2, hal. 230, Daftar Nasyr Islami, Qum, Cetakan Kedua, 1404 H.
[3]. Muhammad Baqir Majlisi, Bihâr al-Anwâr, jil. 10, hal. 78, Dar Ihya al-Turats al-‘Arabi, Beirut, 1403 H.
[4]. (Qs. al-Baqarah [2]:199)
«ثُمَّ أَفیضُوا مِنْ حَیْثُ أَفاضَ النَّاسُ وَ اسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحیم»
[5]. Abdu ‘Ali bin Jum’ah ‘Arusi Huwaizi, Tafsir Nur al-Tsaqalain, jil. 1, hal. 195, Ismailiyan, Qum, Cetakan Keempat, 1415 H.
[6]. (Qs. Taubah [9]:37)
«إِنَّمَا النَّسیءُ زِیادَةٌ فِی الْکُفْرِ یُضَلُّ بِهِ الَّذینَ کَفَرُوا یُحِلُّونَهُ عاماً وَ یُحَرِّمُونَهُ عاماً لِیُواطِؤُوْا عِدَّةَ ما حَرَّمَ اللهُ فَیُحِلُّوا ما حَرَّمَ اللهُ زُیِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمالِهِمْ وَ اللهُ لا یَهْدِی الْقَوْمَ الْکافِرینَ»
[7]. Tafsir Nur al-Tsaqalain, jil. 2, hal. 217.
[8]. (Qs. al-Baqarah [2]:158)
«إِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَّوَّفَ بِهِمَا وَ مَن تَطَوَّعَ خَیْرًا فَإِنَّ اللهَ شَاکِرٌ عَلِیْمٌ»
[9]. Tafsir Nur al-Tsaqalain, jil. 1, hal. 146 & 148.
[10]. Mulla Muhsin Faidh Kasyani, Tafsir Shâfi, Riset oleh Husain A’lami, jil. 2, hal. 192, al-Shadr, Tehran, Cetakan Kedua
Masalah keadilan Tuhan memiliki beberapa cirikhas di antaranya:
-Banyak soal berkaitan dengan masalah ketuhanan, yang hanya bisa dijawab oleh kalangan khusus di atas tingkat awam. Tetapi masalah keadilan Tuhan menjadi perhatian -dan dapat diikuti- semua kalangan, dari yang awam sampai yang pakar.
-Muslimin tidak berselisih tentang sifat-sifat bagi Allah, melainkan tak setajam perselisihan mereka tentang masalah adil. Sampai batas, keyakinan terkait masalah ini membawa identitas bahwa fulan syii atau sunni, dan jika sunni, ia mutazili atau asyari.
Mutazilah dan Syiah meyakini keadilan Tuhan bahwa Dia mustahil berbuat lalim, keduanya dikenal dengan Adliyîn atau Adaliyah. Karena mereka memandang adil sebagai dasar agama. Lalu keduanya terpisah oleh masalah imâmah (kepemimpinan ilahiah) yang dipandang oleh Syiah sebagai dasar lainnya bagi agama.
Asyairah sama sekali tidak mengingkari keadilan Tuhan. Tidaklah mungkin mereka memandang bahwa Allah tidak adil. Yang menjadi persoalan di sini ialah mengenai potensi akal, bahwa ia mampu menjangkau nilai-nilai perbuatan-perbuatan (termasuk perbuatan Tuhan), mana yang harus dilakukan dan yang ditinggalkan. Misalnya, Allah swt memasukkan orang-orang beriman ke dalam surga dan orang-orang kafir ke dalam neraka.
Jadi, titik mendasar perbedaan antara Asyariah dan Adaliyah terletak pada baik dan buruk. Bahwa, perbuatan itu sendiri dalam pandangan Asyarah tidak mensifati baik atau buruk. Baik dalam urusan yang ada (takwini) adalah apa yang Allah lakukan, dan dalam urusan yang diadakan (tasyrii) adalah apa yang Allah perintahkan.
Sedangkan dalam pandangan Adaliyah, perbuatan itu mensifati baik atau buruk. Potensi akal sampai pada pengetahuan sisi-sisi baik dan buruk dalam perbuatan-perbuatan. Rasionalitas ini tak berarti naudzubillah sampai dikatakan- bahwa: akal memberi perintah dan larangan kepada Tuhan. Melainkan ia menyingkap keselarasan dan ketidak selarasan suatu perbuatan dengan kesempurnaan ilahiyah. Atas dasar inilah pandangan akal bahwa mustahil perbuatan buruk dari Allah swt.
Mengapa Keadilan Bagian dari Ushuluddin?
Adil salah satu sifat positif dan kesempurnaan bagi Allah. Alasan bahwa sifat ini dipandang sebagai dasar agama (ushuluddin):
1-Memiliki urgensi yang khas, bahwa banyak sifat yang melazimkan adil atau didasari keadilan. Karena maknanya luas, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya.
2-Keadilan Tuhan mendasari prinsip maad (hari akhir) dan nubuwah yang keduanya sebagai dasar agama, dan konsep imamah yang menjadi dasar mazhab Syiah.
3-Di antara semua sifat Allah, adil terpilih menjadi salah satu dasar agama dalam mazhab Syiah (dengan kata lain, bagian dari dasar-dasar mazhab Syiah), memiliki akar historis dan akar politis:
Yang pertama, telah disinggung di atas mengenai baik dan buruknya perbuatan, Asyarah memandang bahwa apapun yang Allah inginkan dan lakukan adalah baik. Termasuk seandainya Dia memasukkan Imam Ali as ke dalam neraka dan pembunuhnya, Ibnu Muljam, ke dalam surga, terlepas dari pandangan akal bahwa semua perbuatan Tuhan memuat hikmah (bijaksana).
Akal memandang setiap perbuatan Tuhan tidak kontra hikmah walaupun seluruh alam keberadaan adalah milik-Nya, dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu. Allah swt menjanjikan surga bagi para hamba yang saleh, dan neraka bagi kaum yang thâleh (durhaka). Mustahil bagi Allah ingkar janji, dan karena itu buruk maka tak mungkin Dia melakukan keburukan.
Akal menilai bahwa Allah tidak mungkin berbuat lalim, bukan membatasi kemaha kuasaan-Nya. Melainkan hikmah (kebijaksanaan-Nya) lah yang meniscayakan qudrah (kuasa-Nya) pada posisi yang semestinya.
Yang kedua, bertolak pada periode bani Umayah dan bani Abbasiyah, para penguasa untuk mencegah tindakan-tindakan protes, gejolak dan kebangkitan umat, propaganda mereka ialah bahwa segala sesuatu adalah kehendak Allah, termasuk menjadikan mereka berkuasa, dan tak seorang pun yang berhak bicara terhadap kehendak-Nya. Sebab, kekuasaan bagi mereka di dunia ini adalah takdir-Nya (jabr; determinisme), dan tiada pilihan bagi orang-orang yang dikuasai mereka. Determinisme ini membawa keridhaan Allah, dan oleh karena itu apapun yang Allah perbuat adalah adil.
4-Keadilan diangkat sebagai dasar agama, sebuah isyarat untuk menghidupkan keadilan di tengah umat dan perlawanan terhadap segala bentuk kezaliman. Seperti halnya tauhid sebagai cahaya penyeru persatuan dan kesatuan di tengah mereka, untuk mengokohkan satu barisan, maka kepemimpinan para nabi dan imam (as) merupakan kepemimpinan kebenaran di tengah seluruh umat manusia. Oleh karena itu, prinsip keadilan Tuhan di seluruh alam keberadaan, mengisyaratkan keharusan menerapkan keadilan di tengah umat manusia dari segala lapisan.
Referensi:
-Al-Adl al-Ilahi/Syahid Mutahari
-Silsilatu ad-Durus fi al-Aqaid al-Islamiyah/Ayatullah Syaikh Makarim Syirazi
-Durus fi al-Aqidah al-Islamiyah/Ayatullah Syaikh M Taqi Misbah Yazdi
-Adl/Ayatullah Syaikh Muhsin Qara`ati
Dimanakah surah Al-Rum itu diturunkan? Di Mekkah atau di Madinah?
Mengapa surah Al-Rum disebut sebagai surah Makkiyah? Sementara dalam Sunan Al-Tirmidzi disebutkan bahwa surah ini diturunkan setelah hijrah Rasulullah Saw ke Madinah?
Jawaban Global
Kebanyakan mufasir dan ulama Ulum al-Qur'an baik dari kalangan Sunni dan Syiah meyakini bahwa surah Al-Rum itu adalah surah Makkiyah (diturunkan di Mekkah)[1] kecuali ayat 17 dan 18 surah ini yang diturunkan di Madinah.[2]
Adapun riwayat yang disinggung dalam pertanyaan disebutkan di salah satu kitab sahih Ahlusunnah yang menyatakan bahwa surah Al-Rum adalah surah Madaniyah.
Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Said:
"Tatkala kaum Muslim ikut serta dalam perang Badar pasukan Romawi juga menang atas pasukan Persia. Kemudian orang-orang beriman takjub lalu turunlah ayat yang menyatakan: الم غلبَتِ الرُّوم (Alif Lâm Mîm. Telah dikalahkan bangsa Romawi) hingga بِنَصْرِ اللَّهِ "(karena pertolongan Allah)."[3]
Selanjutnya Tirmidzi berkata: "Nashr bin Ali membaca awal surah Al-Rum dengan "ghalabat" (dalam bentuk aktif [ma'lum]). "
Demikian juga Tirmidzi menilai hadis ini sebagai hadis gharib dan hasan.[4]
Riwayat yang dalam pandangan Tirmidzi sendiri merupakan gharib; bersumber dari perbedaan bacaan yang dibaca dalam bentuk aktif yang dalam hal ini menjelaskan kemenangan orang-orang Roma setelah hijrah bukan kekalahan mereka sebelum hijrah!
Namun riwayat ini tidak begitu banyak memiliki pendukung. Ibnu Asyur - salah seorang mufasir Ahlusunnah pada abad keempat belas - berkata:
"Hal demikian, adalah ucapan yang tidak ada seorang pun yang mengikutinya.[5] Demikian juga tiada seorang pun mufasir Ahlusunah yang menerima ucapan ini."[6]
Atas dasar itu, sesuai dengan riwayat dan bacaan masyhur yang memandang ayat "ghulibat" - dibaca secara passif - dapat disimpulkan bahwa surah Al-Rum adalah surah Makkiyah dan sejalan dengan peristiwa-peristiwa sejarah. [iQuest]
[1]. Muhammad bin Hasan, Syaikh Thusi, al-Tibyân fi Tafsir al-Qur'ân, jil. 8, hal. 227, Beirut, Dar al-Ihya al-Turats al-‘Arabi, Tanpa Tahun; Fadhl bin Hasan Thabarsi, Majma' al-Bayân fi Tafsir al-Qur'ân, jil. 8, hal. 459, Nasir Khusruw, Cetakan Ketiga, Tehran, 1372 S; Muhammad bin Umar Fakhrrurazi, Mafâtih al-Ghaib, jil. 25, hal. 79, Dar Ihya al-Turats al-‘Arabi, Cetakan Ketiga, Beirut 1420; Sayid Mahmud Alusi, Ruh al-Ma'âni fi Tafsir al-Qur'ân al-Azhim, jil. 11, hal. 18, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, Cetakan Pertama, Beirut, 1414 H; Abul Qasim Muhammad bin Muhammad Nuwairi, Syarh Thayyibah al-Nasyr fi al-Qirâ'ah, jil. 2, hal. 503, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Cetakan Pertama, Beirut, 1424 H.
[2]. Al-Tibyân fi Tafsir al-Qur'ân, jil. 8, hal. 227; Majma' al-Bayân fi Tafsir al-Qur'ân, jil. 8, hal. 459; Abdullah bin Umar Baidhawi, Anwâr al-Tanzil wa Asrâr al-Ta'wil, jil. 4, hal. 201, Dar Ihya al-Turats al-Arabi, Cetakan Pertama, Beirut, 1418 H.
[3]. "Alif Lâm Mîm. Telah dikalahkan bangsa Romawi. Di negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang. Dalam beberapa tahun (lagi). Bagi Allah-lah urusan sebelum dan sesudah (mereka kalah dan menang itu). Dan di hari itu orang-orang yang beriman bergembira (lantaran suatu kemenangan yang lain). Karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Dia-lah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang." (Qs. Al-Rum [30]:1-5) Muhammad bin Isa Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi, Riset dan annotasi: Ahmad Muhammad Syakir, Muhammad Fuad Abdul Baqi, jil. 5, hal. 343, Syarkah Maktabah wa Mathba' Mustafa al-Babi al-Halabi, Cetakan Kedua, Mesir, 1395. Silahkan lihat, Abdur-Rahman, Ibn Abi Hatim, Tafsir al-Qur'an al-Azhim, Riset oleh: As'ad Muhammad al-Thayyib, jil. 9, hal. 3087, Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, Cetakan Ketiga, Arab Saudi, 1419 H.
«عَنْ أَبِی سَعِیدٍ، قَالَ: لَمَّا کَانَ یَوْمُ بَدْرٍ ظَهَرَتِ الرُّومُ عَلَى فَارِسَ فَأَعْجَبَ ذَلِکَ المُؤْمِنِینَ فَنَزَلَتْ: "الم غُلِبَتِ الرُّومُ" - إِلَى قَوْلِهِ - "یَفْرَحُ المُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ" قَالَ: فَفَرِحَ المُؤْمِنُونَ بِظُهُورِ الرُّومِ عَلَى فَارِسَ».
[4]. Ibid.
«هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِیبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ، کَذَا قَرَأَ نَصْرُ بْنُ عَلِیٍّ "غَلَبَتِ الرُّومُ"»
[5]. Muhammad bin Thahir, Ibnu Asyur, al-Tahrir wa al-Tanwir, jil. 9, hal. 5, Muassaah al-Tarikh, Cetakan Pertama, Tanpa Tahun.
«و هذا قول لم یتابعه أحد».
[6]. Silahkan lihat, Muhammad Tsanaullah Mazhhari, al-Tafsir al-Mazhhari, jil. 7, hal. 221, Maktabah Rusydiyah, Pakistan, 1412 H.
IMAM HASAN AL-MUJTABA AS, PENGAYOM UMAT YANG TABAH
Hari Lahir
Di rumah yang dindingnya berlapiskan tanah, di kota Madinah Al-Munawwarah, seorang cucunda Nabi, Hasan dilahirkan. Hari itu bertepatan dengan 15 Ramadhan. Hasan kecil diasuh dalam haribaan datuknya, Muhammad saw dan ayahnya Ali bin Abi Thalib as, serta ibunya Fatimah Az-Zahra’ as.
Rasulullah saw sangat mencintai Hasan as. Beliau mengatakan, "Hasan bin Ali adalah putraku." Dalam kesempatan yang lain beliau menyatakan, “Hasan adalah permata hatiku di dunia."
Sudah lama kaum muslimin menyaksikan Nabi saw sering membawa Hasan as di pundaknya dan beliau pernah berkata, “Semoga Allah SWT mendamaikan dua kelompok dari kaum muslimin dengan perantaranya.” Kemudian beliau berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku mencintainya, maka cintailah dia dan cintailah orang-orang yang mencintainya." Beliau pun senantiasa mengulang-ulang berita ini, "Hasan dan Husain adalah penghulu para pemuda di surga."
Suatu hari Rasulullah saw melakukan salat di masjid. Kemudian Hasan as menghampirinya, sedang beliau dalam keadaan sujud. Karena ia naik ke atas punggungnya, lalu duduk di leher datuk kinasihnya itu, Rasulullah saw bangun dari sujudnya secara perlahan-lahan sampai Hasan turun sendiri.
Tatkala beliau selesai dari salatnya, sebagian sahabat berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau telah berbuat sesuatu terhadap anak kecil ini yang tidak pernah engkau lakukan kepada yang lainnya."
Nabi menjawab, "Sesungguhnya anak ini adalah jantung hatiku dan anakku ini adalah ‘sayid’ (sang pemimpin). Semoga Allah SWT mendamaikan dua kelompok muslim yang berseteru melalui tangannya."
Perangai Imam Hasan as
Suatu waktu, Imam Hasan as dan Imam Husain as berjalan menuju masjid. Tiba-tiba mereka menyaksikan seorang kakek tua yang sedang berwudhu. Namun, tata cara wudhunya tidak benar.
Imam Hasan as berpikir sejenak, bagaimana cara menunjukkan wudhu yang benar kepada kakek tersebut tanpa harus menyinggung perasaannya. Kemudian, keduanya mendatangi kakek tersebut seolah-olah keduanya sedang bertengkar tentang wudhu siapakah yang benar. Masing-masing mengatakan, "Wudhumu tidak benar!" Kemudian keduanya berkata pada kakek tersebut, "Wahai kakek, berilah keputusan yang bijak untuk kami berdua, mana di antara kami yang wudhunya benar."
Maka, mulailah keduanya berwudhu. Lantas kakek itu mengatakan, "Wudhu kalian semua sudah benar." Kemudian kakek itu menunjuk kepada dirinya sendiri dan berkata, "Hanya kakek yang bodoh inilah yang tidak benar wudhunya, dan kini telah belajar dari kalian berdua."
Pada suatu hari, salah seorang sahabat menyaksikan Nabi saw memanggul Hasan dan Husain di pundaknya. Sahabat itu berkata, "Semulia-mulia unta adalah unta kalian."
Nabi saw menjawab, "Dan Semulia-mulia penunggang adalah mereka berdua."
Ketakwaan Imam Hasan as
Imam Hasan as adalah orang yang paling ‘abid (tekun ibadah) pada zamannya. Ia menunaikan ibadah haji sebanyak 25 kali dengan berjalan kaki.
Bila beliau hendak berwudhu dan shalat, wajahnya menjadi pucat dan tubuhnya bergetar karena takut kepada Allah SWT. Beliau berkata, "Suatu keharusan bagi setiap orang yang berdiri di depan Tuhannya untuk merasa takut, pucat wajahnya, dan gemetar seluruh tubuhnya."
Apabila telah sampai di pintu masjid, beliau menengadahkan wajahnya ke langit dan berkata dengan penuh khusyuk, "Tuhanku inilah tamu-Mu berdiri di beranda pintu rumah-Mu! Wahai Dzat Yang Mahapemurah, telah datang orang yang banyak melakukan keburukan kepada-Mu! Maka hapuskanlah seluruh keburukan yang ada pada diriku dengan kebaikan yang ada di sisi-Mu, Wahai Yang Maha Mulia!”
Kelembutan Imam Hasan as
Pada suatu hari, Imam Hasan as berjalan di tengah keramaian masyarakat. Tiba-tiba di tengah jalan beliau bertemu dengan orang tak dikenal yang berasal dari Syam. Orang tersebut ternyata seorang yang sangat benci terhadap Ahlulbait Nabi saw (nashibi). Mulailah orang itu mencaci maki Imam. Beliau tertunduk diam tidak menjawab sepatah kata pun di hadapan cacian itu, hingga orang itu menuntaskan caciannya.
Setelah itu, Imam as membalasnya dengan senyuman, lantas mengucapkan salam kepadanya sembari berkata, "Wahai kakek, aku kira engkau seorang yang asing. Bila engkau meminta pada kami, kami akan memberimu. Bila engkau meminta petunjuk, aku akan tunjukkan. Bila engkau lapar, aku akan mengenyangkanmu. Bila engkau tidak mememiliki pakaian, aku akan berikan pakaian. Bila engkau butuh kekayaan, aku akan berikan kekayaan. Bila engkau orang yang terusir, aku akan kembalikan. Dan bila engkau memiliki hajat yang lain, aku akan penuhi hajatmu."
Mendengar jawaban Imam Hasan as tersebut, kakek tersebut terperanjat dan terkejut, betapa selama ini ia keliru menilai keluarga Nabi saw. Sejak saat itu, dia sadar bahwa Mu‘awiyah telah menipu dirinya dan masyarakat yang lain. Bahkan Mu‘awiyah telah menyebarkan isu dan fitnah tentang ihwal Ali bin Abi Thalib as dan keluarganya.
Terkesan oleh jawaban Imam as, Kakek itu pun menangis dan berkata, "Aku bersaksi bahwa engkau adalah khalifah Allah SWT di muka bumi ini, dan sesungguhnya Allah Mahatahu kepada siapa risalah-Nya ini hendak diberikan. Sungguh sebelum ini engkau dan ayahmu adalah orang-orang yang paling aku benci dari sekalian makhluk Allah. Tapi, sekarang engkau adalah orang yang paling aku cintai dari segenap makhluk-Nya."
Kakek tersebut akhirnya dibawa oleh Imam as ke rumahnya dan beliau menjamunya sebagai tamu terhormat hingga dia pergi.
Kedermawanan Imam Hasan as
Seorang pernah datang menjumpai Imam Hasan as dan meminta kepada beliau untuk memberi sejumlah uang. Atas permintaan orang itu, Imam as memberikan 50.500 Dirham.
Ketika seorang Arab Badui datang meminta, Imam as berkata, "Berikan apa yang ada dalam laci itu padanya." Di dalamnya didapati 20.000 Dinar, dan segera diberikan kepada orang Badui itu.
Pada suatu hari, Imam Hasan as melakukan tawaf di Ka’bah. Tiba-tiba beliau mendengar seseorang yang sedang berdoa kepada Allah SWT agar memberinya rezeki sebanyak 10.000 Dirham. Kemudian beliau pergi ke rumahnya, lantas mengirimkan 20.000 Dirham untuknya.
Diriwayatkan, seseorang menjumpai Imam Hasan dan berkata, "Aku telah membeli seorang budak dan ia melarikan diri dariku." Mendengar itu, beliau lekas memberinya delapan orang budak sebagai ganti budaknya yang hilang itu.
Khilafah (Kepemimpinan Islam)
Segera setelah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib menemui kesyahidan pada 21 Ramadhan akibat tebasan pedang Ibnu Muljam, kepemimpinan Islam beralih ke pundak putranya, yaitu Imam Hasan as. Peralihan ini disambut oleh kaum muslimin saat itu dengan menyatakan baiat (ikrar setia) kepada beliau. Ketika itu, beliau baru berusia 27 tahun.
Pada pagi hari, di awal peralihan kepemimpinan umat itu, Imam as naik ke atas mimbar dan memberikan pidato tentang sejarah, kelangsungan kepemimpinan politik ayahnya dalam memperjuangkan keadilan, kesetaraan, dan menantang setiap makar para pengkhianat agama.
"Sungguh telah diambil nyawanya pada malam itu. Dialah manusia yang orang-orang sebelumnya belum pernah mengunggulinya dalam beramal, dan orang-orang setelahnya pun tak sanggup melakukan amalan tersebut. Sungguh ia berjuang bersama Rasulullah dan telah menjaganya dengan dirinya, dan Rasulullah memberikan panji Islam kepadanya. Sedang malaikat Jibril menjaganya dari sisi kanan dan malaikat Mikail dari sisi kirinya. Dan beliau tidak pernah kembali sehingga Allah SWT membuka dan memperlihatkan kemenangan kepadanya. Sungguh beliau telah syahid di malam ketika Isa bin Maryam as dimikrajkan dan di malam ketika Yusya’ bin Nun, sang penerus Musa as pergi menghadap Allah SWT.”
Kemudian air mata Imam Hasan as luruh membasahi pipinya. Tangisan beliau telah membuat orang-orang yang hadir saat itu juga ikut menangis.
Lalu Imam as melanjutkan pidato, “Aku adalah putra dari pemberi kabar gembira (basyir). Aku adalah putra pemberi peringatan (nazdir). Aku adalah putra penyeru ke jalan Allah (da'i). Aku adalah putra pelita yang cerlang (sirajun munir). Aku adalah bagian keluarga Nabi (Ahlulbait) yang Allah telah jauhkan dari segala kotoran dari diri mereka dan telah mensucikan mereka sesuci-sucinya.
"Aku termasuk Ahlulbait yang Allah SWT telah mewajibkan orang-orang untuk mencintainya sebagaimana firmannya, ‘Katakanlah [wahai Muhammad]! ‘Aku tidak meminta upah apa pun dari kalian atas risalah ini kecuali kecintaan kepada keluargaku.’ Dan barang siapa melakukan suatu kebaikan, maka akan Kami tambahkan baginya suatu kebaikan.’” (QS. Asy-Syura: 22)
Tak lama setelah itu bangkitlah Abdullah bin Abbas dan berkata, “Ketahuilah wahai sekalian manusia, inilah putra Nabimu dan penerima wasiat dari Imammu. Maka, berbaiatlah kepadanya!"
Serempak orang-orang menjawab seruannya dan bergegas untuk memberikan baiat kepada Imam Hasan as.
Muslihat dan Makar Mu‘awiyah
Sementara itu, Mu‘awiyah secara terus-menerus melancarkan makar dan penentangan terhadap Imam Hasan as. Sebagaimana pada masa Imam Ali as, perang Shiffin dan perang Nahrawan adalah bentuk pembangkangannya terhadap khalifah muslimin, dan usahanya dalam rangka merampas tampuk kepemimpinan umat Islam dari tangan pemimpinnya yang sah.
Masyarakat telah memilih Imam Hasan as sebagai khalifah Rasulullah saw, dan sebagai pemimpin mukminin. Akan tetapi, Mu‘awiyah menentang dan menolak baiat kepadanya. Alih-alih menunjukkan ketaatan, dia malah menyebarkan mata-matanya ke Kufah dan Bashrah, serta mengirimkan uang guna membeli hati beberapa orang dekat beliau.
Imam Hasan as tidak menganggap remeh makar yang dilakukan oleh Mu‘awiyah. Bahkan, beliau memerintahkan untuk menghukum mati para mata-mata Mu‘awiyah. Kemudian beliau mengirimkan surat ancaman kepada Mu‘awiyah agar ia menghentikan penyimpangan dan penentangannya.
Persiapan Perang
Selain melakukan makar, Mu‘awiyah mengerahkan seluruh tentaranya untuk menebarkan rasa takut di hati kaum muslimin. Tak segan-segan ia menyerang mereka serta merampok seluruh harta benda miliknya. Imam Hasan as berupaya untuk melawan dan bersiap-siap menyusun barisan perang.
Di hadapan kaum muslimin, Imam mengatakan, “Sesungguhnya Allah SWT telah menetapkan jihad untuk makhluknya dan menjadikan jihad tersebut sebagai sebuah kewajiban. Kemudian Allah SWT mengatakan kepada mujahidin, “Bersabarlah! Karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, dan kalian tidak akan mendapatkan apa yang kalian inginkan kecuali dengan kesabaran atas apa yang kalian tidak inginkan. Berangkatlah! Semoga Allah SWT menaungi kalian!”
Sayang sekali, rasa takut telah menguasai mereka sehingga sambutannya untuk ikut berperang begitu dingin. Maka, di sinilah Adi bin Hatim At-Tha’i, salah seorang sahabat Imam as, bangkit sambil berteriak lantang dan mencemooh mereka, “Akulah Adi bin Hatim! Maha Suci Allah, Duhai ... alangkah jijiknya tempatku ini! Tidaklah kalian sambut seruan Imam dan putra Nabi kalian."
Sebagian pembela Imam Hasan bangkit dan memberi semangat kepada masyarakat untuk bersiap-siap menghadapi Mu‘awiyah. Hingga tersusunlah pasukan berjumlah dua belas ribu prajurit. Pasukan ini dipimpin oleh Ubaidillah bin Abbas yang kedua putranya telah dibunuh oleh Mu‘awiyah.
Sayangnya, di dalam tubuh pasukan Imam Hasan as sendiri terdapat banyak orang yang rakus akan dunia, sehingga Mu‘awiyah begitu mudahnya membeli mereka dengan kepingan Dirham dan Dinar, dan mereka pun begitu mudahnya membelot ke pasukan Mu‘awiyah.
Bahkan, Mu‘awiyah telah berhasil menyuap panglima perang Imam Hasan as, Ubaidillah bin Abbas dengan uang sebesar satu juta Dirham. Lantas ia pun berkhianat dan membelot dari pasukan beliau. Dia lebih memilih berdiri di barisan Mu‘awiyah dan rela membiarkan beliau bangkit sendiri.
Imam Hasan as memahami betapa sulitnya menghadapi Mu‘awiyah dengan pasukan-pasukan yang lemah imannya itu. Mereka merelakan dijualbelikan diri dan agamanya dengan harga yang amat rendah. Dari sinilah Mu‘awiyah menawarkan perdamaian kepada Imam as, dengan syarat beliau harus turun dari kekhalifahan.
Di samping itu, Imam Hasan as tahu bahwa dengan meneruskan perlawanan terhadap Mu‘awiyah malah akan membawa kehancuran dan kematian sahabat-sahabat serta pembela-pembela setia beliau yang sebagiannya adalah sahabat-sahabat mulia Nabi saw. Belum lagi tentara Syam yang akan menduduki Kufah. Semua itu turut melengkapi kekuatiran Imam as.
Perdamaian
Orang-orang Khawarij telah merencanakan siasat untuk membunuh Imam Hasan as yang ternyata mendapat dukungan Mu‘awiyah dari jauh, dengan maksud memaksa Imam Hasan as menerima usul perdamaian dan turun dari kursi kekhalifahan.
Imam as tidak memikirkan selain kepentingan Islam dan kemaslahatan umatnya. Maka itu, demi menghindari pertumpahan darah, Imam as dengan terpaksa menyepakati perdamaian itu, dan menulis butir-butir perdamaian, di antaranya:
1. Hendaknya Mu‘awiyah bertindak sesuai dengan Al-Qur’an dan Sunah Nabi.
2. Hendaknya tidak melakukan pencaci-makian terhadap Ali bin Abi Thalib.
3. Mu‘awiyah tidah berhak untuk menentukan seorang pun untuk menduduki khilafah.
4. Tidak memaksa Imam Hasan untuk mengakui Mu‘awiyah sebagai Amirul Mukminin.
5. Hendaknya Mu‘awiyah mengembalikan kekhalifahan kepada Imam Hasan as, dan bila Imam as telah meninggal, maka kekhalifahan dikembalikan kepada Imam Husain as.
Mu‘awiyah Merobek Surat Perdamaian
Sebelumnya, Imam Hasan as telah mengetahui bahwa Mu‘awiyah tidak akan menjalankan butir-butir yang tercantum dalam perdamaian tersebut. Akan tetapi, beliau hendak menunjukkan kepada umat tentang akal bulus Mu‘awiyah, bahwa dia adalah orang yang tidak teguh pada janji dan agama.
Perjanjian damai telah dilaksanakan. Segera setelah memasuki kota Kufah, Mu‘awiyah naik ke mimbar dan berpidato di depan khalayak seraya mengatakan, “Sesungguhnya aku tidak membunuh, tidak juga angkat senjata, atau menyerbu kalian supaya kalian berpuasa atau melakukan salat. Akan tetapi, tujuanku agar aku memimpin kalian. Ketahuilah, bahwa setiap butir yang tertulis dalam surat perdamaian itu sekarang ada di bawah telapak kakiku." Dengan cara secongkak itu Mu‘awiyah menginjak-injak perdamaian.
Selanjutnya, Mu‘awiyah menentukan Ziyad bin Abih sebagai gubernur Kufah. Ia mulai mengusir pengikut Ahlulbait, menghancurkan rumah-rumah mereka, merampas harta benda mereka, hingga menyiksa dan memenjarakan mereka.
Imam Hasan as berupaya untuk membantu orang-orang yang teraniaya, dan menentang seluruh perbuatan zalim Mu‘awiyah yang telah melanggar butir-butir perdamaian sebagaimana yang telah diberikan kepadanya.
Sampai pada saatnya, Mu‘awiyah merencanakan pembunuhan terhadap Imam Hasan as dan berupaya untuk mendudukkan anaknya yang bernama Yazid di atas kursi kekhalifahan. Dalam rangka itu, ia berpikir untuk meracuni beliau.
Untuk menjalankan rencana pembunuhan tersebut, Mu‘awiyah memilih Ja‘dah, istri Imam Hasan as, yang ayahnya adalah seorang munafik. Tentunya setelah mengiming-imingi imbalan harta kekayaan dan menjadi istri putra mahkota, Yazid.
Setan mulai menggoda pikiran Ja‘dah. Ia pun bersedia menerima racun yang dikirimkan Mu‘awiyah untuknya, lalu mencampurkannya ke dalam makanan yang telah dipersiapkan untuk buka puasa. Karena saat itu Imam as sedang berpuasa.
Tiba saatnya berbuka puasa. Imam Hasan as mulai berbuka dengan makanan yang telah disediakan oleh Ja‘dah. Tiba-tiba ia merasakan pedih dan sakit. Pengaruh racun itu membuat usus beliau terkoyak. Kemudian ia menatap istrinya dan berkata, “Wahai musuh Allah! Kau telah membunuhku. Semoga Allah membunuhmu. Sungguh Mu‘awiyah telah memperdaya dan menipumu. Semoga Allah menghinakanmu dan menghinakannya (Mu‘awiyah).”
Dan demikianlah kenyataannya. Mu‘awiyah tidak menepati janjinya kepada Ja‘dah. Ia berhasil menipu Ja‘dah dan bahkan mengusirnya dari istana. Mu‘awiyah berkata kepadanya, “Kami lebih cinta pada Yazid!” Begitulah nasib Ja‘dah. Ia menderita di dunia dan akhirat. Sejak saat itu, ia lebih dikenal dengan julukan "Si Peracun Suami".
Karena tak lagi kuasa menahan jahatnya racun tersebut, akhirnya Imam Hasan as gugur sebagai syahid pada 28 Shafar 50 H. Dan di hadirat Allah kelak, beliau akan mengadukan kezaliman Bani Umayyah terhadap dirinya.
Jasad suci Imam Hasan as dikebumikan di pemakaman Baqi‘, di Madinah Al-Munawwarah.[]
Riwayat Singkat Imam Hasan as
Nama : Hasan.
Gelar : Al-Mujtaba.
Panggilan : Abu Muhammad.
Ayah : Ali bin Abi Thalib.
Ibu : Fatimah.
Kelahiran : Madinah, 15 Ramadhan 3 H.
Usia : 47 tahun.
Syahid : 28 Shafar 50 H.
Makam : Pemakaman Baqi‘, Madinah.
MENGAPA BERTAWASHUL KEPADA PARA KEKASIH ALLAH DILARANG?
Sejenak kita saksikan beberapa fatwa Ulama Wahabi terkait bertawasul.
Syaikh Abdul Aziz bin Baz seorang mufti terkemuka Hijaz mengatakan bahwa: “tawasul pada kedudukan, maqom dan berkah atau hak seseorang adalah sebuah bid’ah tapi bukan syirik. Jadi tidak dibenarkan siapapun yang berkata ‘Allahumma inni bijahi Nabiyika/ bijahi awliyaika fulan…’ atau ‘bihaqi fulan’ atau ‘bibarkati fulan…’, hal ini merupakan bid’ah dan condong kepada kesyirikan meskipun tidak sampai pada derajat syirik.” (Majmu’ Fatawa wa Maqalat mutanawi’ah, syaik Ibn Baz, jil. 4 hal. 311)
Syaikh Soleh bin Fauzan berkata: “barang siapa yang beriman pada sifat Khaliq dan Raziq Allah swt. namun diwaktu yang sama ia menempatkan seorang perantara antara dia dengan Tuhannya, maka ia telah melakukan bid’ah… dan jika ia bertawasul (kepada jah/maqam atau kedudukan mereka disisi Allah swt.) tanpa menyembah mereka, maka ini adalah bid’ah yang diharamkan dan ang mengantarkan pada kesyirikan…” (al-Muntaqi min Fatawa as-Syaikh Ibn Fauzan, jil 2 hal. 54) 1338
Nashiruddin Al-Bani: “Saya berkeyakinan bahwa barang siapa yang bertawasul kepada Awliya, Shalihin dan lainnya, maka ia telah melenceng dari jalan kebenaran (agama)…” (Fatawa al-Baani, hal. 432)
Wahabi yang mengaku mengikuti ulama salaf dan ingin memurnikan Islam dari ‘inovasi-inovasi’ ibadah yang tidak ada pada zaman Nabi maupun Sahabat, sudah terlalu banyak mempermasalahkan amalan-amalan yang dilakukan oleh Muslimin pada umumnya. Inovasi-inovasi tersebut mereka sebut Bid’ah, Salah satunya yaitu tawasul seperti fatwa yang telah dikemukakan sebelumnya. Secara umum alas an bid’ah adalah yang paling sering digunakan oleh kaum tersebut. Padahal dalam memahami makna bid’ah itu sendiri perlu pendalaman yang intensif karena disana masih terdapat perbedaan pandangan dari sisi makna maupun misdaq-nya.
Lalu apakah benar tawassul itu diharamkan (karena menjurus pada kesyirikan)? Apakah tawassul ini sesuai dengan ajaran dan sunnah Rasulullah saw.?
Sebenarnya sudah banyak sanggahan atas syubhat yang dilemparkan oleh para pengikut Abdullah bin Wahab ini, namun tidak ada salahnya kita lebih menggali lagi untuk memantapkan keyakinan atas kebenaran hakiki dari salah satu ibadah Muslimin ini.
Tawassul sendiri memiliki makna bahwa seorang hamba menempatkan sesuatu atau seseorang sebagai perantara antara dia dengan Allah swt. yang mengantarkannya untuk lebih mendekatkan diri kepada-Nya. Wasilah/perantara pada dasarnya memiliki 2 jenis yaitu materi seperti air dan makanan yang menjadi perantara menghilangkan kehausandan rasa lapar dan non-materi seperti Allah mengampuni dosa seorang hamba ketika ia menjadikan Nabi sebagai perantara dalam memintakan ampunan untuk dirinya.
وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوّاباً رَحِيماً
“…sekiranya mereka setelah menzalimi dirinya dating kepadamu (Muhammad), lalu memohon ampunan kepada Allah dan Rosul pun memohon ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang.” (QS. An-Nisa: 64)
Penting untuk difahami bahwa tatanan penciptaan tidak lepas dari sebab akibat atau illat dan ma’lul dan ini tidak terbatas pada hal yang bersifat materi saja, hidayah dan ampunan yang merupakan anugerah dari Allah swt. pun tidak lepas dari tatanan ini. Aturan ini bersumber dari ke-Maha Bijaksanaan Tuhan dalam menciptakan sebaik-baiknya penciptaan; (Yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah,) (QS. Sajdah: 7)
Al-Quran banyak menyinggung masalah ini salah satunya ayat yang berbunyi:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah (jalan) untuk mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah (berjuanglah) di jalan-Nya, agar kamu beruntung.” (QS. Al-Maidah: 35)
Melalui kisah-kisah teladan yang terekam dalam Quran, Allah swt menyinggung berbagai hal yang berkaitan dengan menjadikan seseorang sebagai perantara untuk mengantarkan hamba-Nya pada kedekatan kepada Allah swt. seperti pada kisah Nabi Musa dan Nabi Muhammad saw ketika menjadikan arah kiblat sebagai wasilah untuk memfokuskan diri diharibaan-Nya.
Allah swt. berfirman:
قَدْ نَري تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمّا يَعْمَلُونَ
“Kami melihat wajahmu (Muhammad) sering menengadah ke langit, maka akan Kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi Kitab (Taurat dan Injil) tahu, bahwa (pemindahan kiblat) itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan.” (QS.Al-BAqarah: 144) n
وَأَوْحَيْنا إِلي مُوسي وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءا لِقَوْمِكُما بِمِصْرَ بُيُوتاً وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ
“Dan Kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, “Ambillah beberapa rumah di Mesir untuk (tempat tinggal) kaummu dan jadikanlah rumah-rumahmu itu tempat ibadah dan laksanakanlah shalat serta gembirakanlah orang-orang mukmin.” (QS. Yunus: 87)
Seorang hamba yang mengingkari sebab-akibat yang merupakan bagian dari penciptaan, berarti ia mengingkari wujud penciptaan itu sendiri dan telah berpaling dari hikmah Tuhan yang dengannya menciptakan alam semesta. Syahid Muthahari berkata bahwa setiap Fi’il Allah memiliki aturan dan hikmah, dan jika seorang hamba tidak memperhatikan aturan ini maka dia telah bermaksiat.
Terakhir, ada riwayat yang dinukil dari Usman bin Hanif mengatakan bahwa ada seorang yang buta mendatangi Rasulullah saw. dan meminta padanya untuk berdoa kepada Allah untuk kesembuhannya. Beliau bersabda: “Jika kamu mau bersabar, maka itu lebih baik bagimu. Namun jika kamu mau aku akan mendoakanmu.” Orang yang buta tersebut berkata: “aku ingin Anda berdoa untuk kesembuhanku.” Rasulullah saw menyuruhnya untuk berwudhu dan berdoa seperti ini,
«اللّهمّ إنّي أسألك وأتوجّه إليك بنبيّك محمّد نبيّ الرحمة، يا محمّد! إنّي توجّهت بك إلي ربّي في حاجتي ليقضيها، اللّهمّ شفّعه فيّ»
Semua ini adalah bentuk dari bertawasul kepada Allah swt. yang terekam dalam Al-Quran maupun Riwayat, jadi tidaklah benar mengatakan bahwa tawassul/menjadikan hamba Sholeh sebagai perantara mendekatka diri pada Allah adalah ‘inovasi’ dalam ibadah yang tidak ada pada zaman Nabi dan Sahabat. Sekiranya dalam hal ini perlu pemahaman lebih dalam dengan merujuk kitab-kitab muktabar supaya memantapkan keyakinan kita dalam menjalankan ibadah tanpa terpengaruh oleh syubhat-syubhat musuh Islam baik di luar ataupun tubuh Islam itu sendiri.